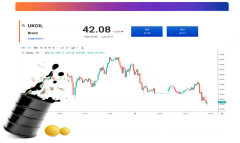Catatan Cak AT: Menjaga Konstitusi Ilmu

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Pekan lalu, saya menulis catatan pendek tentang siwak. Ya, siwak — kayu harum mungil yang, kalau dipakai sebelum salat, bisa mengubah aroma mulut dari “asap rokok sisa sahur” menjadi “miswak certified.”
Dalam catatan itu, saya mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang terkenal: “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap hendak salat.”
Waktu itu, saya fokus pada aspek kesehatan — bahwa kandungan alami kayu siwak dapat menghilangkan bau mulut yang, dalam salat berjamaah, hembusannya bisa mengganggu rekan di sebelah.
Tapi pekan ini, saya menemukan lapisan pemahaman baru yang menggetarkan dari Gus Baha. Dia mengajak kita melihat hadits siwak bukan sekadar dari sisi adab atau etika, melainkan dari sudut konstitusi ilmu.
Baca juga: Adakah Korupsi Rp 1,25 triliun di ASDP?
Bayangkan, bahkan terhadap sesuatu yang sangat disukai Nabi — sesuatu yang secara etika nyaris wajib — beliau menahan diri untuk tidak mewajibkannya. Kenapa? Karena beliau paham, dalam ilmu itu ada yang disebut ijtihad, dan ada pula istitha’ah (kemampuan).
Maka Nabi, yang secara otoritas kenabian bisa saja menerbitkan dekrit syar’i soal siwak, justru memilih menggunakan redaksi “seandainya tidak memberatkan umatku...”
Luar biasa. Ini bukan sekadar kerendahan hati, tapi satu langkah besar dalam menjaga agar agama tidak berubah menjadi agama beban. Islam itu agama yang pasti. Yang wajib, ya wajib. Yang sunnah, ya sunnah. Maka yang tidak wajib jangan dipaksa-paksakan seolah wajib.
Kita hidup di zaman di mana banyak orang merasa jadi penjaga otoritas agama. Bahkan yang belum selesai ngaji tafsir al-Fatihah pun kadang sudah berani bikin daftar wajib versi sendiri. Apa saja bisa naik pangkat: dari sunah jadi “wajib sosial”.
Baca juga: ESG dan K3 di Industri Pelayaran: Menjaga Laut, Menyelamatkan Nyawa
Gus Baha, ulama yang gaya bicaranya santai tapi tajam, menyebut ini sebagai penyakit klasik dalam ilmu: “Ijābu mā lam yajib” — mewajibkan sesuatu yang tak wajib. Celakanya, justru inilah awal dari otoritarianisme agama: lembut di permukaan, tapi melumpuhkan di dalam.
Orang-orang pun mulai merasa bersalah hanya karena tidak ikut wiridan maraton versi mayoritas. Merasa berdosa karena bubar lebih awal setelah salat. Bahkan merasa maksiat karena tak mengikuti arah imam yang “lebih afdhal” — padahal arah kiblatnya tetap pas.
Mari kita loncat ke satu isu sederhana yang bisa bikin konflik kecil di musala komplek: usai salat, imam harus menghadap ke mana?
Ke timur? Ke utara? Tetap ke kiblat? Atau balik badan sambil baca notifikasi WhatsApp?
Baca juga: Selamat Datang Hari Puisi Indonesia sebagai Hari Besar Nasional
Gus Baha mengulas ini dalam channel Ngugemi Ulama dengan kisah yang menawan. Faktanya, Nabi Saw kadang menghadap ke jamaah setelah salat. Alasannya bukan gaya, tapi sistem komunikasi zaman unta.
Bayangkan ada sahabat yang datang dari jarak jauh — 7 kilometer — demi salat berjamaah bersama Nabi. Kalau Nabi setelah salat tetap menghadap kiblat, mereka yang datang belakangan bisa menyangka: “Wah, salat masih berlangsung!” Lalu ikut takbir, padahal Nabi sudah salam dan bubar.
Solusinya? Nabi “aqbala ‘alainā biwajhihi” — beliau menoleh, menghadap ke jamaah, untuk memberi maklumat bahwa salat telah selesai. Ini bukan sekadar gestur, tapi pengumuman visual yang penting. Seolah berkata, “Sudah salam, bro. Salatnya selesai.”
Ulama yang memahami konteks ini pun bersikap fleksibel. Usai salam, kadang mereka tetap menghadap kiblat, kadang ke utara, kadang ke jamaah. Jadi yang fanatik madep ngetan maupun yang jumud madep ngalor, sejatinya sedang salah paham dalam memaknai fleksibilitas Nabi.
Baca juga: Catatan Cak AT: Impor GMO, Impor Penyakit
Yang penting: jangan dijadikan wajib, apalagi sampai bikin banner "Setelah salat harap menghadap utara."
Sekarang mari kita masuk ke fase pasca-salat. Di sinilah pertunjukan paket kombo dimulai. Semua wirid Nabi yang berserakan dalam berbagai hadits diramu jadi satu kesatuan.
Tasbih ada, tahmid ada, takbir lengkap. Doa panjang berlanggam qasidah ikut masuk. Makmum yang niatnya buru-buru malah bingung:
“Ini masih wiridan atau sudah muqaddimah maulid?”
Padahal, kata Gus Baha, Nabi Saw kadang hanya membaca istigfar tiga kali lalu pergi. Ringan, sah, dan tetap khusyuk. Tapi karena semua versi disatukan, lalu dijadikan standar, maka yang tidak ikut akan dicurigai seperti melanggar rukun Islam keenam: wiridan full paket.
Baca juga: Terang Aksara Empowerment, Program Pemberdayaan Disabilitas PLN Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta
Separuh jamaah akhirnya ngeloyor diam-diam — bukan karena tak cinta zikir, tapi karena harus kerja, jemput anak, atau lapar. Dan ini bukan aib, melainkan bentuk menjaga agar "yang tidak wajib tidak menjadi wajib" secara sosial.
Di titik ini kita paham: Nabi adalah penjaga konstitusi ilmu terbaik. Beliau cinta qiyamulail, dan sering salat malam di masjid. Tapi ketika para sahabat mulai ikut, beliau malah tidak keluar rumah lagi.
Kenapa? Karena takut ibadah sunah itu dianggap sebagai kewajiban.
Kalau kita yang jadi Nabi? Mungkin sudah bikin spanduk besar:
“Tiada malam tanpa qiyamulail berjamaah. _No excuse!”_
Dan jangan kaget kalau ada kiai-kiai kita yang sengaja tidak puasa Senin-Kamis — bukan karena tak suka, tapi karena tak ingin umat menyangka bahwa itu wajib hanya karena mereka melakukannya.
Hal yang sama berlaku pada doa qunut. Ia adalah sunah muakkadah, bukan syarat sah salat. Tapi kalau tiap hari disertai qunut panjang dan dianggap mutlak, akhirnya jadi beban — bukan rahmat.
Islam itu luwes. Yang wajib, ya wajib. Yang sunah, ya sunah. Dan yang tidak wajib? Jangan digeret jadi wajib hanya demi mempertahankan gengsi kealiman.
Dalam menjaga agama, kita mesti meneladani Nabi: bijak, sabar, konstitusional. Jangan sampai karena terlalu semangat beramal, kita justru menciptakan syariat baru yang memberatkan orang lain — lalu merasa itu bagian dari dakwah.
Baca juga: UI dan PT KAI Soroti Upaya Konservasi Geopark dan Pelestarian Elang Jawa
Agama ini diturunkan sebagai rahmat, bukan sebagai sistem level-up spiritual yang mengharuskan wiridan 33x mode turbo.
Maka ketika Gus Baha bicara tentang konstitusi ilmu, yang beliau jaga bukan hanya hukum, tapi juga akal sehat dan ruang bernapas umat.
Jangan-jangan, yang kita butuhkan hari ini bukan ulama baru, melainkan ulama yang menjaga agar agama tetap seperti sedia kala: ringan, rasional, dan tidak memberatkan. (***)
Penulis: Cak AT — Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 24/7/2025


 Nasional - 06 Nov 2025
Nasional - 06 Nov 2025