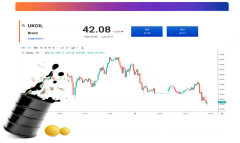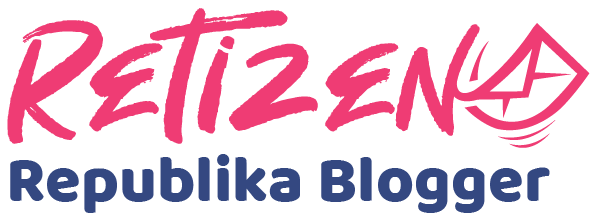Catatan Cak AT: Impor GMO, Impor Penyakit
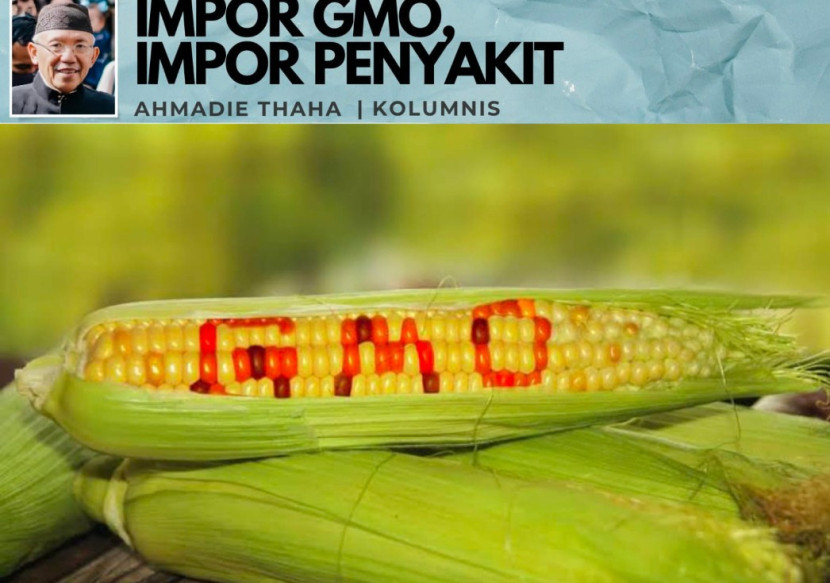
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Dari Missouri ke meja makan warteg, dari glyphosate ke ginjal rakyat —bagaimana kesepakatan dagang justru melemahkan petani dan membahayakan kesehatan.
“Indonesia Bubar 2030?” tulis seorang kawan di grup WhatsApp, nada suaranya dramatik, seperti narator trailer film kiamat. Yang lain langsung menyambut dengan meme: gambar Donald Trump menaburkan biji gandum di ladang Nusantara, senyum lebar di wajahnya, dengan caption: “Habis manis, sepahit pestisida.”
Lucu, tapi tidak sepenuhnya lelucon. Sebab, setelah Presiden Prabowo Subianto bersalaman erat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump —yang dalam tradisi diplomasi dikenal dengan istilah “pegangan tangan beracun”— kita benar-benar menyaksikan babak baru dari tragedi pangan dan pertanian nasional. Bahkan kiamat kesehatan.
Baca juga: UI dan PT KAI Soroti Upaya Konservasi Geopark dan Pelestarian Elang Jawa
Angka tak bisa dibantah: impor produk pertanian dari AS melonjak drastis, dari 2,9 miliar dolar menjadi 4,5 miliar dolar hanya dalam setahun.
Kenaikan sebesar 55 persen ini bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi isyarat arah kebijakan yang kian menjauh dari kedaulatan pangan.
Ironisnya, sebagian besar dari bahan pangan yang membanjiri Indonesia ini berbasis tanaman transgenik alias GMO. Mungkin kita tak terlalu sadar, karena label di kemasan makanan tak pernah jujur menyebutkan asal-usul genetis bahan bakunya.
Tapi faktanya jelas: kedelai yang kita jadikan tempe, tahu, bahkan kecap, sebagian besar datang dari AS dengan nilai impor 1,25 miliar dolar. Ladang-ladang kedelai di Missouri, AS, memasok kebutuhan kedelai kita. Dari luar AS tentu ada pula.
Baca juga: Pengasuh dan Alumni Ponpes Babakan Layangkan Maklumat atas Kebijakan Gubernur Jabar
Gandum yang menjadi bahan dasar mi instan dan roti, juga menelan biaya impor besar. Belum termasuk bungkil kedelai, pakan ternak, susu, daging sapi, dan —entah kenapa— kapas. Ya, kapas pun kita impor, entah untuk dijahit atau dikunyah.
Impor jagung pun tak mau ketinggalan. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mengimpor 1,3 juta ton jagung. Mayoritas memang dari Argentina dan Brasil, tapi AS telah berjanji akan mulai mengalirkan lebih banyak jagungnya —yang juga GMO— ke Indonesia tahun depan.
Perlahan tapi pasti, kita kini lebih banyak makan dari ladang Dakota dan Texas ketimbang dari sawah-sawah Wonosobo atau ladang jagung di Blitar. Sementara itu, para petani kita? Masih mencangkul dengan alat warisan Mbah Lurah, menyaksikan lahan-lahan mereka kian tergusur oleh banjir pangan impor.
Dari sisi sebaliknya, ekspor kita ke AS sebenarnya hanya menumpu pada satu komoditas unggulan: minyak sawit atau CPO. Tarifnya memang kini lebih bersahabat, turun jadi 19 persen setelah sebelumnya dikenakan 32 persen —lebih kompetitif dibandingkan tarif Malaysia yang mencapai 25 persen.
Baca juga: Depok Susun Rencana Aksi Penanganan Stunting Tepat Sasaran
Tapi mari jujur, siapa yang menikmati insentif ini? Petani kecil di pelosok Kalimantan yang menanam sawit dengan tangan sendiri? Atau para pemilik kebun raksasa yang bisa menyeruput kopi di _rooftop_ hotel sambil memantau harga CPO lewat Bloomberg?
Diversifikasi pangan, yang selama ini didengungkan oleh akademisi dan pegiat pertanian, justru dilindas oleh kebijakan perdagangan yang hanya menguntungkan segelintir eksportir dan importir besar. Sementara itu, kedelai lokal tetap tak mampu bersaing, dan jagung lokal dihargai di bawah ongkos produksi.
Sebagian orang mungkin masih bertanya: “Apa salahnya makan kedelai atau gandum GMO? Toh sehat-sehat saja?”
Nah, ini yang perlu dijelaskan. Tanaman GMO —terutama dari AS, Argentina, dan Brasil— adalah produk rekayasa genetika agar tahan terhadap pestisida berbasis glyphosate, seperti RoundUp.
Baca juga: Baznas Depok Ajak Kolaborasi RS Hermina dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis ZIS
Artinya, tanaman-tanaman ini bisa disemprot pestisida dalam dosis tinggi, dan tetap tumbuh kuat, seperti Rambo. Tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita bukan cuma kedelainya, melainkan juga residu pestisidanya.
Badan Kesehatan Dunia, melalui IARC, telah mengklasifikasikan glyphosate sebagai zat yang “kemungkinan besar bersifat karsinogenik pada manusia”. Jadi, sambil makan tempe, kita juga mungkin sedang menyantap risiko kanker.
Studi dari jurnal _Environmental Sciences Europe_ pada 2019 juga mengonfirmasi bahwa konsumsi jangka panjang GMO dan pestisidanya berpotensi merusak fungsi hati dan ginjal. Celakanya, di Indonesia, tak ada kewajiban label "GMO" di kemasan produk pangan. Kita makan dalam gelap.
Tak heran, jika kemudian muncul lonjakan kasus penyakit ginjal kronis di Indonesia. Data dari WHO menyebutkan bahwa angka kematian akibat gagal ginjal kronis naik dari 1,4 juta pada tahun 2019 menjadi 8,7 juta jiwa pada tahun 2023.
Baca juga: Muslim yang Tercerahkan
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) juga mencatat kenaikan prevalensi penyakit ginjal dari 2 persen pada 2013 menjadi 3,8 persen pada 2018. Kita boleh saja menyalahkan gaya hidup, tapi jangan abaikan fakta bahwa tubuh kita mungkin sudah lama dijejali pangan murah dengan residu kimia mahal.
Dan di tengah kenyataan itu, Indonesia tetap menjadi pengimpor gandum terbesar di Asia Tenggara. Ketergantungan kita sudah melampaui 11 juta ton per tahun.
Padahal, gandum tak pernah akrab dengan iklim tropis. Tapi karena masyarakat makin gandrung pada mi instan, roti putih, dan kudapan berbasis gandum, kita rela menggantungkan perut pada petani di Kansas dan Illinois —yang bahkan tak tahu letak Indonesia di peta.
Kesepakatan dagang Trump-Prabowo hanya memperparah ketergantungan itu. Gandum GMO kini masuk lebih murah dan deras, bahkan sampai ke dapur-dapur warteg di pinggiran kota.
Baca juga: Catatan Cak AT: Mas Menteri Core Team
Perlahan namun pasti, gandum menggeser nasi, jagung, singkong, dan umbi-umbian lokal. Maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa kedaulatan pangan kini hanya hidup dalam pidato-pidato, bukan di ladang dan meja makan.
Sementara para petani lokal mencaci harga yang terus jatuh, pabrik tahu di Blitar makin tenggelam dalam ketergantungan pada kedelai Missouri.
Guru-guru Biologi masih mengajarkan anak-anak tentang pentingnya keanekaragaman hayati, tetapi kebijakan perdagangan yang nyata justru mendorong homogenisasi pangan, monokultur pertanian, dan ketergantungan tunggal pada sistem pangan global yang tak bisa kita kendalikan.
Kalau begini terus, bukan tak mungkin, beberapa tahun lagi, tumpeng akan berubah jadi artefak museum. Anak-anak akan bertanya, “Ayah, dulu nasi kuning itu dari padi? Apa itu padi?” Dan sang ayah, dengan mata berkaca-kaca, akan menjawab lirih, “Itu dulu, Nak. Sekarang kita makan Pasta Bhineka, hasil kolaborasi antara Monsanto dan McDonald’s.”
Baca juga: Peserta Pertamina UMK Academy Naik Kelas Lebih Cepat Lewat Platform Learning Management System
Karena itu, kita tak bisa diam. Ini bukan cuma soal menolak impor, tapi soal menuntut hak kita sebagai bangsa. Kita perlu kebijakan pangan yang transparan, pelabelan yang jujur, dukungan nyata bagi petani lokal, serta pembatasan keras terhadap produk-produk GMO yang meragukan.
Kita perlu membangun sistem pangan yang sehat, mandiri, dan beragam. Jika tidak, kita sedang menggali liang kubur sendiri —dengan sendok plastik sekali pakai, berisi gandum transgenik. (***)
Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 23/7/2025


 Nasional - 06 Nov 2025
Nasional - 06 Nov 2025