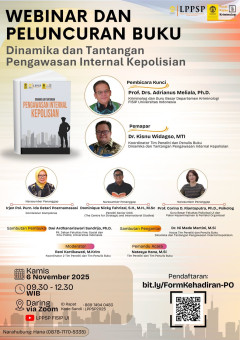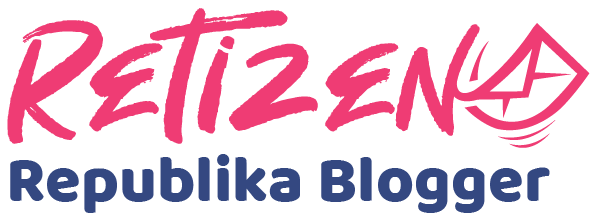Tinjauan Sosiologis Terhadap Gelombang Protes di Indonesia

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Indonesia diguncang gelombang amarah rakyat setelah kematian Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang menjadi simbol kerentanan pekerja urban tanpa kepastian penghasilan maupun perlindungan sosial.
Tragedi ini memicu protes luas, dengan kemarahan tumpah dalam bentuk perusakan simbol negara dan penyerangan fasilitas publik serta properti pribadi tokoh-tokoh publik. Pertanyaannya adalah mengapa demikian?
Program Studi Sosiologi Universitas Nasional menegaskan bahwa protes ini bukan sekadar gejolak kerusuhan, melainkan cermin transformasi besar dalam kehidupan sosial-politik Indonesia kontemporer, yang menuntut keadilan sosial dan perbaikan tata kelola perkotaan.
Uraian berikut merangkum pokok kertas posisi yang membaca gelombang protes dari sudut sosiologis-historis: bukan sekadar kerusuhan, melainkan ekspresi politik rakyat akibat akumulasi ketidakadilan, rapuhnya kelas menengah, dan tersumbatnya representasi. Analisis ini menjadi pijakan kebijakan yang lebih adil dan responsif.
Baca juga: Catatan Cak AT: Bukan Sekadar 'Bubarkan DPR'
Ringkasan Tinjauan
1. Reportoar aksi kolektif. Gejolak pada akhir Agustus–awal September 2025 bukanlah ledakan spontan, melainkan kelanjutan dari tradisi panjang tindakan kolektif rakyat.
Charles Tilly (2006) menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki repertoar protes—serangkaian cara bertindak yang dipelajari, diulang, dan dikenali oleh rakyat maupun negara. Karena itu, peristiwa ini tidak dapat dianggap anomali, melainkan sebuah bab baru dalam kosakata politik jalanan Indonesia.
2. Pergerseran lokus protes rakyat. Gejolak itu juga menunjukkan fakta penting bahwa secara historis lokus protes rakyat di Indonesia telah bergeser.
Jika dulu pemberontakan kerap muncul dari desa agraris—pada abad ke-19 hingga 1960-an—kini keresahan lahir dari kota, produk urbanisasi besar sejak awal 2000-an. Kota menghadirkan janji mobilitas sosial, tetapi juga memunculkan ketidakpastian hidup, solidaritas sosial yang rapuh, serta kedekatan dengan simbol kuasa yang terasa timpang.
Baca juga: Bersama Ojek Online Garut Bersatu, Pemkab Garut Gelar Doa Bersama
Peristiwa Jakarta pun bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari rangkaian demonstrasi yang menolak kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat dan mempersempit demokrasi.
3. Aksi yang terpola. Apa yang tampak sebagai aksi spontan sesungguhnya mengikuti pola yang telah berulang sejak Reformasi 1998.
Mahasiswa kerap menjadi pemantik, membuka ruang bagi rakyat yang lebih luas untuk ikut serta, hingga bentrokan dengan aparat menjadi klimaks
terantisipasi (Aspinall, 2013). Urbanisasi cepat, ketimpangan sosial-ekonomi, dan rapuhnya kota menciptakan lahan subur politik jalanan (Hadiz, 2010).
Baca juga: Masa Tantang Ketua DPRD Majalengka Baca Pancasila, Responsnya Bikin Tepuk Tangan Meriah
Karena itu, ledakan kemarahan 2025 bukan kejutan, melainkan ekspresi politik rakyat sahih atas ketidakadilan struktural.
4. Kotradiksis sosial-ekonomi yang menumpuk di perkotaan menjadi akar ledakan protes Jakarta pada Agustus 2025.
Urbanisasi besar-besaran menjadikan kota pusat mobilitas sosial, tetapi juga ruang penuh ketidakpastian: biaya hidup melambung, solidaritas sosial melemah, dan kanal politik tersumbat (Bauman, 2000).
Kelas menengah, pilar demokrasi, menyusut dari 57,3 juta jiwa (2019) menjadi 47,9 juta (2024) (Katadata, 2025). López-Calva & Ortiz-Juárez (2014) menyebut kondisi ini sebagai “rentan jatuh miskin.” Bersamaan, pekerja gig economy tanpa perlindungan dasar menanggung beban serupa.
Baca juga: 1.240 Orang Pendemo Anarkis Ditangkap, Kapolda: Mereka dari Luar Jakarta
5. Memburuknya kondisi ekonomi rakyat. Biaya hidup yang tinggi, upah minimum tak mencukupi, dan gelombang PHK memperburuk keadaan.
Data Kemnaker yang dikutip Katadata (2025) mencatat 42.385 kasus PHK hingga Juni 2025, naik 32% dari tahun sebelumnya. Banyak pekerja terpaksa masuk sektor informal tanpa perlindungan, memperdalam jurang antara elite dan rakyat. Protes perkotaan pun menjadi ekspresi keras krisis representasi dengan adanya sumbatan dalam sistem politik yang tidak lagi dapat menjadi saluran aspirasi suara rakyat.
6. Partai politik tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Alih-alih menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, partai justru beroperasi layaknya kartel elektoral yang sibuk dengan transaksi pasca-pemilu.
Ketika keresahan rakyat meledak di jalanan, tidak ada partai yang mampu mengantisipasi maupun menenangkan massa; mereka memilih diam, menjadi penonton, dan bahkan takut berhadapan dengan rakyat yang marah.
Baca juga: Wali Kota Depok Supian Suri Pesan ke Para Ortu Agar Anaknya Tak Ikut Aksi Demo
7. Media membentuk persepsi dan daya kekuatan aksi. Media arus utama cenderung menyoroti aspek kekerasan dan “anarkis,” sehingga menutupi akar struktural seperti beban hidup dan krisis representasi politik.
Sebaliknya, media alternatif dan platform digital menghadirkan narasi tandingan melalui video amatir, unggahan personal, dan siaran langsung yang menyoroti sisi kemanusiaan, terutama tragedi Affan Kurniawan.
Teknologi digital mempercepat penyebaran amarah: isu lokal di Jakarta dengan cepat meluas ke Makassar, Yogyakarta, dan kota lain.
Media, karenanya, menjadi arena perebutan wacana antara kriminalisasi protes dan legitimasi politik rakyat.
Baca juga: Catatan Cak AT: Epitaf Urban ACAB 1312
8. Tergerusnya jaminan pengaman sosial dan kohesivitas masyarakat urban Indonesia. Urbanisasi masif telah mengikis solidaritas desa tanpa menghadirkan pengganti yang kokoh di kota, membuat individu tercerabut dari jaring pengaman sosial dan hidup dalam kondisi cair serta rapuh sebagaimana digambarkan Bauman.
Dalam situasi ini, tindakan massa bukanlah deviasi, melainkan bahasa terakhir mereka yang kehilangan suara.
9. Gaya hidup pamer elite politik kian mencolok di tengah kesenjangan sosial yang semakin terasa. Para pejabat tampil dengan fasilitas negara yang mewah, mulai dari kendaraan dinas, rumah dinas, hingga perjalanan luar negeri dengan biaya tinggi yang ditanggung rakyat.
Sirene kendaraan dinas yang memaksa jalanan terbuka lebar di tengah kemacetan menjadi simbol sehari-hari betapa privilese kekuasaan begitu kontras dengan penderitaan warga yang harus bergulat dengan biaya hidup.
Pola hidup konsumtif dan demonstrasi kemewahan ini bukan sekadar soal etika, tetapi menegaskan jarak kuasa antara elite dan rakyat, sekaligus memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Penutup
Apa yang kita saksikan di jalanan Jakarta bukan sekadar huru-hara, melainkan cermin rapuhnya kontrak sosial masyarakat urban Indonesia.
Seperti diingatkan Emile Durkheim, masyarakat modern hanya bertahan bila solidaritas sosial terpelihara.
Namun urbanisasi massif telah meruntuhkan solidaritas desa tanpa menghadirkan pengganti di kota, meninggalkan individu dalam kondisi rapuh sebagaimana digambarkan Bauman dengan istilah liquid modernity.
Pemerintah tidak bisa lagi hanya menegur atau menakut-nakuti rakyat setiap kali keresahan sosial meledak. Yang dibutuhkan adalah membuka kanal deliberatif melalui forum publik, konsultasi warga, dan musyawarah terbuka yang memberi ruang suara rakyat.
Baca juga: Ingin Pantau Langsung Kondisi Tanah Air, Prabowo Batal ke China
Dialog langsung mengenai apa yang salah, apa yang perlu dikurangi atau diganti, lebih bermakna dibanding retorika lama tanpa solusi.
Ketika kepercayaan pada negara melemah, masyarakat sipil—kampus, organisasi sosial, lembaga independen—masih dapat menjadi ruang alternatif bagi rakyat.
Keberanian pemerintah untuk mendengar dan melibatkan masyarakat akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan kontekstual.
Sebagai penutup kertas posisi ini, beberapa pokok penting sebagai tindak lanjut yang bisa dilakukan yang menopang kehidupan masyarakat demokratis, bermartabat, dan berkeadilan adalah:
Baca juga: Pendemo di Makassar Ngamuk, Gedung DPRD Sulsel Ludes Dibakar
1. Aksi massa yang berujung pada perusakan simbol elit harus dipahami sebagai ekspresi politik elementer rakyat yang kehilangan kanal representasi. Pemerintah perlu berhenti menstigma dengan label “anarkis” atau “makar” dan mulai mengakuinya sebagai gejala sosial yang menuntut jawaban struktural.
2. Urbanisasi di Indonesia selama dua dekade terakhir telah melahirkan masyarakat cair yang rapuh ikatan sosialnya.
Negara dan pemerintah kota perlu menciptakan ruang-ruang deliberasi warga dalam bentuk forum warga lintas komunitas, koperasi komunitas, dan forum partisipasi yang memperkuat kembali modal sosial di kota.
3. Hambatan struktural politik yang menjadikan komunikasi antara rakyat dan pemerintah telah menjadi dasar frustasi warga terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak peka pada persoalan masyarakat.
Baca juga: Pengunjukrasa Bakar Halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya, CCTV Dirusak
Pemerintah harus membentuk sebuah forum di perkotaan yang menjadi ruang perbincangan tentang kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat antara pemerintah dan warga.
4. Beban pajak dan upah minimum yang tidak layak adalah faktor utama keresahan. Diperlukan reformasi pajak yang lebih adil serta kebijakan upah dan perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan pekerja informal, dan pengendalian biaya hidup.
5. Negara perlu memastikan tersedianya lapangan kerja yang layak, terlindungi, dan berkesinambungan agar tenaga produktif tidak terjebak dalam lingkaran kerentanan, melainkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi dan demokrasi, serta mencegah jangan sampai terjadi informalisasi kerja pada usia produktif.
6. Mekanisme demokrasi elektoral perlu diperbaiki untuk mampu menyalurkan aspirasi rakyat kecil. Perlu inovasi agar rakyat merasa suaranya didengar sebelum harus turun ke jalan.
Baca juga: Catatan Cat AT: Chaos Tiga Kali
7. Respons represif terbukti hanya memperkuat siklus kekerasan. Aparat harus dilatih untuk menggunakan strategi de-eskalasi, dialog, dan pendekatan komunitas, sehingga konflik tidak berkembang menjadi bentrokan terbuka.
8. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi lubang kekosongan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus menciptakan mekanisme yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegakkan hukum.
9. Situasi sekarang menyebabkan lembaga-lembaga politik formal seperti Parlemen dan Partai Politik telah kehilangan kemampuan dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Perguruan Tinggi sebagai wakil masyarakat sipil dapat berperan menjahit kembali pola relasi sosial yang tercabik, dan mengawasi serta mengawal lahirnya kebijakan yang berorientasi pada rakyat, adil, dan inklusif. (***)
Kertas Posisi Program Studi Sisiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Jl. Sawo Manila 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sosiologi@civitas.unas.ac.id


 Bisnis - 04 Nov 2025
Bisnis - 04 Nov 2025