Catatan Cak AT: Sebelas Frasa Cahaya Tauhid
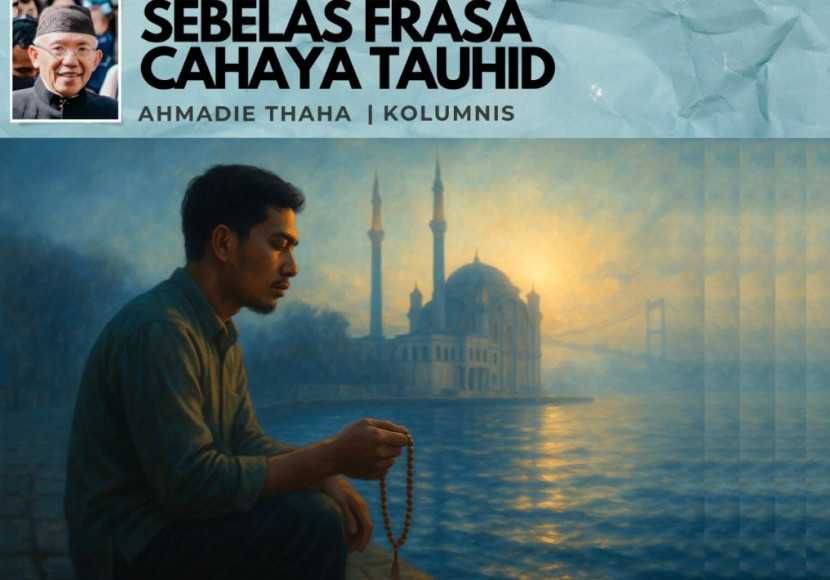
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Sudah lama saya membaca kalimat itu setiap pagi, sebagaimana ribuan orang lainnya: lafaz yang akrab di bibir. Di tengah rutinitas shubuh yang setengah mengantuk, lidah ini mengulang:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
(Tiada Tuhan selain Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Dia pemilik seluruh kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia Mahahidup; tidak mati. Di tangan-Nya tergenggam segala kebaikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu dan kepada-Nya semua kembali.)
Menariknya, kalimat ini ditinggikan maknanya oleh para sufi dan ulama, sebab ia ditegaskan langsung oleh Rasulullah ﷺ dalam banyak riwayat.
Ia disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari dan juga dari Mu‘ādz bin Jabal — sebagaimana tercantum dalam Musnad Ahmad, Sunan an-Nasa’i, dan Sahih Ibn Hibban.
Baca juga: Yuk! Seru-seruan Wisata Malam Hari di Taman Margasatwa Ragunan, Buka Mulai 11 Oktober
Nabi menjanjikan pahala besar bagi siapa yang membacanya sepuluh kali (hadis lain menyebut "seratus kali") setiap pagi atau setelah magrib: dicatat sepuluh kebaikan, dihapus sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh derajat, seolah membebaskan empat orang budak, dan dijaga dari setan hingga waktu berikutnya.
Kalimat itu sudah akrab —kita sering membacanya tiap pagi sebagai dzikir shabah.
Tetapi di Hayrat Vakfi, di sebuah meja kayu yang penuh goresan, saya mendengar sesuatu yang membuat lafaz yang sama terdengar baru.
Menurut Syeikh Badiuzzaman Said Nursi dalam karyanya al-Maktubat, kalimat ringkas itu merupakan rangkaian sebelas frasa. Setiap frasa seperti lilin kecil yang bila dinyalakan meruntuhkan gelap di satu titik jiwa.
Baca juga: Tembus Pasar Brunei Darussalam, Produk UMKM Difabel Cassava Crackers Mendunia
Kawan saya dari Hayrat, ustadz Cemal Sahin, menutup naskah lama itu dan berkata, “Kalau kau pikir itu hanya lafaz, berarti kau belum membaca peta yang ada di dalamnya.” Di Üsküdar, Istanbul, di kamar kecil di lantai tiga asrama Hayrat Vakfi, saya membaca peta itu.
Dalam perjalanan pulang ke kamar penginapan saya memegang secarik kertas kecil berisi pembagian frasa menurut Nursi. Saya ulangi pelan, bukan untuk menghafal, melainkan untuk mengizinkan makna menelusup pelan ke dalam urat nadi.
Saya akan menuturkannya di sini satu per satu. Tapi jangan bayangkan penuturan saya seperti daftar kering. Biarkan tiap frasa mengalir seperti cerita pendek yang menyulut ingatan, mungkin mempermudah pemahaman ketimbang membaca langsung dari _al-Maktubat_ yang agak rumit.
Pertama, di ayat itu ada pengakuan mutlak: Lā ilāha illallāh. Di sini dimulai semua pembebasan. Ketika mulut mengucapnya, ia memecah semua berhala yang kita bangun sendiri: bukan lagi sekadar batu atau patung, tapi berhala bergaya modern —status, akun, prestise— yang meracuni kesederhanaan.
Baca juga: Mahasiswa UI Raih Penghargaan "Begadang Filmmaking Competition" di Minikino Film Week 2025
Nursi menaruh awal tauhid di situ: pengakuan bahwa doa, pengharapan, dan penghambaan hanya layak ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita membaca ini cepat-cepat sambil membayangkan gaji yang belum datang, berarti kita membaca setengah hati; bedanya cuma seutas niat.
Kedua, lafaz _waḥdahu_ — “Dia sendirilah” — memampatkan keesaan menjadi kenyataan yang meresap: tidak ada sekutu dalam hakikat dan tindakan-Nya. Bila kau masih mencari sekutu dalam keputusan hidupmu —mentor, koneksi, “insta-guru”— maka frasa ini menampar pelan: otoritas terakhir bukan manusia, melainkan Zat yang sendirilah yang menentukan arus. Di sana letak kebebasan: bila kau menemukan-Nya sebagai sandaran, segala takut akan manusia mereda.
Ketiga, _lā sharīka lahū_ membawa kelegaan yang lain: bukan sekadar menolak sekutu filosofis, tapi menafsirkan bahwa Rububiyyah-Nya adalah tanpa perantara. Dalam dunia di mana birokrasi memanjang dan “perantara” menikmati komisnya, frasa ini memerdekakan jiwa: tidak ada kemacetan antara hajat dan Tuhan, kecuali kita membuatnya sendiri lewat ragu dan takabur.
Keempat, ketika datang kalimat _lahu al-mulk_, tiba keinsafan pemilikan total: "kerajaan" ini bukan milik kita. Lucunya, kita berlagak sebagai direktur utama hidup sendiri —menandatangani semua keputusan seolah semua aset milik pribadi— padahal kita hanyalah pekerja harian yang diberi tugas untuk sementara.
Baca juga: Semangat Pengabdian UI Jadi Ruang Inklusif Bagi Sahabat Disabilitas
Said Nursi mengajak kita melihat dunia bukan sebagai gudang kepemilikan, melainkan sebagai amanah: kerja yang membuat kita berzikir kalau paham posisinya.
Kelima, _wa lahu al-ḥamd_ menyalakan nada syukur: segala puji semata untuk-Nya. Ini bukan sekadar lafaz ritual; ia adalah kacamata untuk melihat rahmat yang terselip di balik kegagalan, dan memberi rasa bahwa bahkan kehilangan terkadang adalah pintu kepada nikmat lain.
Saya sering melihat jamaah yang mengucap “Alhamdulillah” dengan nada klausa, “Alhamdulillah, tapi ”. Said Nursi menggeser ucapan hamdalah itu menjadi pujian yang murni, tanpa syarat, sebuah tindakan estetika hati.
Keenam dan ketujuh, pembacaan beralih ke kuasa penciptaan: yuḥyī lalu wa yumītu. Di sini hidup dan mati tidak lagi menjadi musuh; keduanya adalah dua sisi pekerjaan Tuhan. Hidup yang diberi adalah amanah, mati yang datang adalah pembebasan tugas.
Baca juga: Pesawat Tanpa Awak XAG, Lompatan Penting Budi Daya Padi di Indonesia
Dalam percakapan dengan salah seorang pembaca Rasāil al-Nur, saya mendengar cara beliau menafsirkan kematian bukan sebagai tragedi final melainkan sebagai panggilan pulang yang wajar —sebuah ironi lembut buat mereka yang memegangi hidup seperti tiket konser yang tak bisa dipulangkan.
Kedelapan, pernyataan wa huwa ḥayyun lā yamūt menyodorkan paradoks pemeliharaan: Tuhan itu hidup hakiki; kita hanya menerima kilasan kehidupan dari-Nya.
Di tengah manusia yang berlenggang dengan teknologi yang mencoba “membuat hidup abadi” lewat data dan memori, Said Nursi mengingatkan: keabadian yang sejati bukan di server atau memori flash, melainkan di Zat yang tidak pernah mengalami kehilangan napas.
Kesembilan, bi yadihi al-khayr memberi keyakinan bahwa segala kebaikan berada di tangan-Nya. Pembacaan ini menaruh kembali arti upaya: bekerja bukan sia-sia; kebaikan yang tampak kecil akan menjadi besar bila Allah menghendaki.
Baca juga: Catatan Cak AT: Fiskal Peredam Kejut
Saya teringat seorang tukang teh di Istanbul yang berkata singkat: “Kamu bikin teh untuk orang, tapi keberkahan bukan di gelas, melainkan di tangan yang memberi.” Begitu juga amal kita: bentuknya kecil, hasilnya rahasia.
Kesepuluh, _wa huwa ‘alā kulli shay’in qadīr_ adalah obat untuk kegelisahan modern: tidak ada perkara yang berat bagi-Nya.
Saat manusia sombong ingin memprogram hujan, mengedit gen, atau mendesain nasib, frasa ini mengundang kita kembali kepada kerendahan: ada hal-hal yang hanya pantas ditanggung oleh Tuhan. Tugas kita adalah tawakal yang cerdas, bukan ambisi yang merusak.
Kesebelas, penutup yang menengahkan: wa ilayhi al-maṣīr — kepada-Nya segalanya kembali. Ini bukan kalimat puitis semata melainkan jangkar eksistensial. Di ujung usaha dan lelah, di titik kebahagiaan dan duka, ada tujuan yang memberi bentuk artinya perjalanan.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Kabinet Merah Putih Sering Reshuffle, Kapan Menterinya Bekerja?
Said Nursi menempatkan frasa ini sebagai penutup yang mengikat semua frasa sebelumnya menjadi satu alur: pengenalan, penyerahan, kepemilikan, pujian, hidup, mati, kuasa, dan kembali.
Di meja kecil medrasa Hayrat, kawan saya menutup buku dan menatap laut yang memisah dua benua. “Kita sering membaca ini setiap pagi,” katanya, “tapi membaca pagi tidak sama dengan hidup pagi. Yang membedakan adalah: apakah kalimat itu mengubah cara kau berpakaian jiwa, mengubah cara kau memegang dompet dan mengucap selamat tinggal.” Saya tersenyum, menyeruput teh yang kini terasa seperti obat.
Perjalanan ke Turki beberapa tahun lalu bukan sekadar perjalanan geografis. Untuk saya, ia adalah perjalanan pulang: pulang pada makna yang tiap pagi berbisik di bibir kita tapi terlalu sibuk ditelan rutinitas.
Sekarang, ketika saya mengulang kalimat itu, saya sengaja memberi jeda antar frasa —segar seperti menyirami tanaman rohani yang selama ini terabaikan. Kadang harus pergi jauh untuk menyadari bahwa yang kita cari itu sudah lama ada di asbak doa kita sendiri.
Baca juga: Siap Berdamai, Hamas Serahkan Daftar Tahanan Palestina ke Israel
Semoga pembacaan kecil ini, yang merangkum sebelas cahaya tauhid menurut Al-Maktubat, bukan hanya menambah informasi tetapi menjadi bahan renungan dan, bila dimatangkan di rumah ibadah, menjadi khotbah yang menenangkan.
Karena di balik retorika politik, di balik bising pasar digital, ada kalimat ringkas yang, bila dipahami, mampu membuat manusia kembali menjadi manusia yang tenang. (***)
Penulis: Cak AT — Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 10/10/2025


 Bisnis - 31 Oct 2025
Bisnis - 31 Oct 2025




