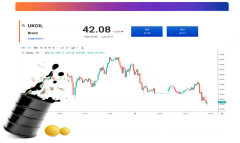In Memoriam Wina Armada, Hoax dan Kematian Kebenaran

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- "Hoax bukan sekadar kebohongan. Ia perusak tatanan sosial. Ia memicu kebencian, fitnah, dan perpecahan. Dan yang lebih berbahaya, ia menyamar sebagai kebenaran.”
Kutipan itu terngiang kuat saat saya menerima kabar wafatnya Wina Armada, Kamis sore, 3 Juli 2025.
Ia bukan sekadar kolega di Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena, tapi jurnalis, ahli hukum, sekaligus sahabat sejati—teguh dalam prinsip, lembut dalam pergaulan.
Berulang kali Wina menyerukan: sanksi atas penyebaran hoax tak boleh lunak. Harus tegas. Harus berat.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas pers, tapi kelangsungan akal sehat publik.
Baca juga: Catatan Cak AT: Ekonomi Tumbuh Loyo
-000-
Tiga hari sebelum ia wafat, saya mengirim pesan resmi ke enam WAG Satupena, mengajak semua mendoakan kesembuhannya.
Bagi yang Muslim, dengan Al-Fatihah. Bagi yang non-Muslim, dengan doa menurut keyakinannya.
Putrinya mengirimkan ucapan terima kasih kepada saya melalui japri WA, atas bunga yang saya kirim mewakili teman-teman.
Saya sempat meneleponnya. “Apakah Wina sudah bisa ditengok?” Ia menjawab lembut, “Belum, Om. Kata dokter, belum boleh.”
Saya melanjutkan, “Apakah beliau sudah sadar?” Ia menjawab pelan, “Masih belum sadar, Om.”
Baca juga: Kabar Gembira, Gubernur KDM Usulkan Optimalisasi 50 Siswa per Kelas SMAN/SMKN
Kepada Ilham Bintang, saya bertanya lewat pesan teks, “Bro, seberapa parah serangan jantung Wina? Sudah sepuluh hari belum juga boleh dijenguk?” Jawabnya pendek, tapi menusuk, “Agaknya parah.”
Dua hari kemudian, berita duka itu datang. Sunyi. Wina wafat.
-000-
Di tahun 2017, di panggung World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center, Wina berdiri bukan untuk merayakan, tapi memperingatkan.
Dalam diskusi bertajuk “Memerangi Hoax, Memperkuat Media Siber Nasional,” ia mengucapkan satu kalimat yang tak terlupakan:
“Jika masih ada insan pers menyebarkan atau membuat hoax, sanksi baginya harus diperberat.”
Baca juga: Kemenag dan BAZNAS Kerja Sama Program Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid
Itu bukan sekadar seruan moral. Itu alarm etik. Di era ketika satu genggaman tangan bisa menyebar kebohongan ke jutaan orang, Wina mengingatkan bahwa pers tidak bisa ikut larut dalam kebisingan tanpa verifikasi.
Teknologi adalah keniscayaan, kata Wina. Tapi di balik kemudahan itu, lahir pula para “wartawan abal-abal.”
Itu istilah untuk mereka yang tak terlatih, tak terikat etika, hanya mengejar kecepatan, bukan kebenaran.
“Jurnalisme bukan hanya soal menyebarkan informasi,” ucapnya, “tapi soal tanggung jawab.”
Apa yang membuat Wina mengeluarkan peringatan itu?
Baca juga: Tingkatkan Peluang Kesembuhan, UI dan Siloam Hospitals Adakan Skrining dan Edukasi Kanker Payudara
Ia memahami bahwa struktur masyarakat telah berubah. Dulu, hanya pers yang bisa menyebar berita massal. Kini, semua orang bisa.
Tapi tak semua orang punya integritas jurnalistik. Demokratisasi informasi tanpa kesadaran etik melahirkan lahan subur bagi hoax.
Ia juga mencemaskan kemunduran industri berita. Media cetak melambat, iklan beralih, dan pers profesional kehilangan pijakan.
Dalam kekacauan itu, hoax tak lagi sekadar gangguan. ia menjelma menjadi pengganti kebenaran.
Baca juga: Menkum: Presiden Prabowo Subianto Berharap PWI Bersatu dan Solid
Karena itu, bagi Wina, sanksi tak bisa lagi bersifat administratif. Ia harus menjadi penanda tegas bahwa penyebaran hoax dari dalam tubuh pers adalah pengkhianatan pada profesi.
Sejarah membuktikan betapa berbahayanya hoax.
Tahun 1994, Rwanda dihancurkan oleh radio RTLM yang menyebar hoax dan ujaran kebencian. Kelompok Tutsi disebut “kecoa.”
Hasilnya: dalam 100 hari, 800.000 jiwa tewas. Semua bermula dari siaran-siaran yang menyalakan amarah dan menghapus kemanusiaan.
Kata-kata bisa menjadi peluru. Hoax bisa membunuh, tak hanya karakter, tapi juga tubuh.
Baca juga: WEPACK Southeast Asia Debut Pameran Industri Kemasan di Indonesia Akhir Juli Ini
-000-
Mengapa gagasan Wina perlu kita dukung?
Pertama, karena pers adalah pilar terakhir kebenaran. Jika mereka yang seharusnya menjadi penjaga justru ikut menyebar dusta, kepada siapa publik bisa percaya?
Kedua, karena tanpa etika, profesi ini akan kehilangan legitimasi. Keistimewaan pers datang dari publik. Jika publik kecewa, pers tak lagi punya taji moral.
Ketiga, karena sanksi bukan hanya hukuman, ia juga peringatan. Ketika ada harga yang harus dibayar, maka akan lahir kehati-hatian. Tak ada lagi ruang bagi mereka yang menjual kebohongan demi klik.
Wina juga mengusulkan didirikannya pusat informasi anti-hoax yang independen, bebas dari kendali pemerintah. Ia membayangkan lembaga yang tak bekerja dengan sensor, tapi dengan data.
Tempat kebenaran diverifikasi, dan kebohongan dilucuti, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejelasan.
Baca juga: Catatan Cak AT: Tanda Perang Akan Kembali
-000-
Kita hidup di zaman ketika informasi mengalir deras seperti hujan. Di tengah hujan itu, kata Wina, kita tak butuh ember hoax. Kita butuh payung etik.
Jika kita gagal membedakan keduanya, kebenaran tak akan mati karena dibunuh, tapi karena dibiarkan.
Selamat jalan, Wina Armada.
Selamat jalan, sahabatku.
Jakarta, 3 Juli 2025
Penulis oleh: Denny JA
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, bisnis dan marketing, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/1KxXs9SV2z/?mibextid=wwXIfr


 Nasional - 06 Nov 2025
Nasional - 06 Nov 2025