Catatan Cak AT: Penjurusan Reborn, Menghidupkan Stigma
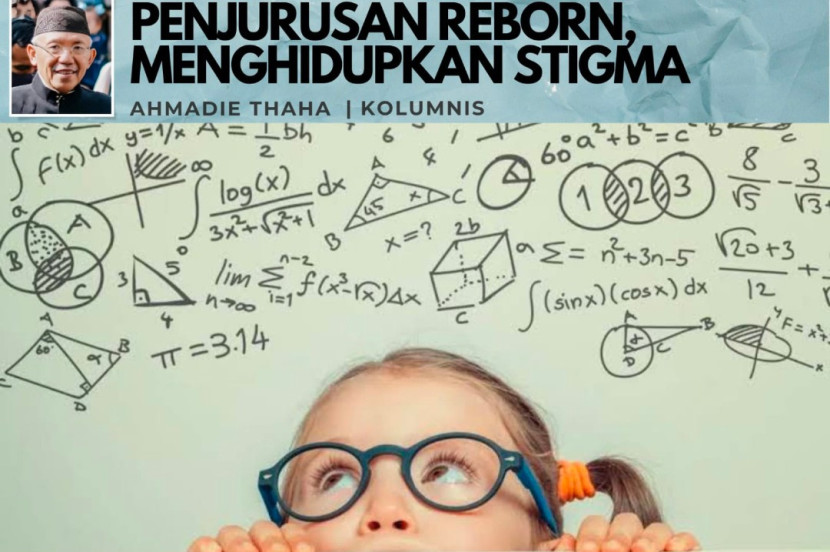
RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Tepuk tangan dulu untuk Kementerian Pendidikan kita tercinta! Di tengah semarak Kurikulum Merdeka yang baru seumur jagung, kini muncul ide cemerlang yang bikin kita semua bernostalgia: mari kita kembalikan penjurusan! Ini muncul seolah menegaskan, setiap ganti menteri ganti pula kebijakan.
Ah, penjurusan. Sang legenda. Sang nostalgia. Sang pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dengan banyak tanda tanya. Seolah negeri ini belum cukup rumit dengan Ujian Sumatif Tengah Semester yang rasanya seperti tes masuk NASA, kini kita akan kembali ke zaman di mana anak SMA harus memilih: menjadi ilmuwan, ekonom, atau penyair gagal—eh, maksudnya jurusan Bahasa.
Tentu saja ini bukan sekadar ide. Ini kebijakan yang, katanya segera dibuat, didasarkan pada keluhan lapangan.
Baca juga: Catatan Cak AT: 'Jumbo' Terbang, Ekosistem Animasi Tertinggal
Lucu sekali, sebuah kebijakan pendidikan tingkat nasional hendak dibuat hanya karena keluhan lapangan dari segelintir orang, bukan didasarkan kajian akademik dan ilmiah.
Iya, katanya siswa bingung memilih mata pelajaran. Saking bingungnya, mereka yang minat di seni bisa-bisanya nyasar ke kelas Biologi Molekuler, dan yang bercita-cita jadi ekonom malah ambil Fisika karena teman sebangkunya ikut.
Kalau itu bukan prestasi dari kebebasan yang tanpa arah, saya tidak tahu lagi apa namanya.
Jadi, untuk mengatasi kebingungan itu, solusi dari Pak Mendikdasmen adalah... menghapus pilihan, meskipun sebetulnya mengambil suatu jurusan adapah pilihan juga.
Baca juga: Catatan Cak AT: Tragedi Digital di Ujung Malam
Brilian! Logikanya mirip seperti: “Karena banyak orang salah memilih pasangan, maka pernikahan akan diatur langsung oleh RT.”
Baiklah, mari kita bicara serius sedikit. Benar bahwa kebebasan dalam Kurikulum Merdeka menuntut kesiapan sistem. Tapi apakah solusi dari kebebasan yang tak terarah adalah membatasi kebebasan itu sama sekali? Atau sebenarnya kita yang malas membangun sistem pendampingan?
Saya pribadi mencoba jalan lain. Saya menyusun asesmen minat dan bakat berbasis Multiple Intelligences. Cukup 90 pertanyaan Ya/Tidak, lalu aplikasi kami memetakan potensi siswa secara lebih ilmiah. Dan tahukah Anda hasilnya?
Banyak siswa yang tadinya ngotot “aku anak IPA, Kak!” ternyata punya dominasi di kecerdasan interpersonal dan musikal. Tapi mereka memilih IPA karena... yah, karena kata ibu tetangga IPA itu masa depan cerah.
Baca juga: Catatan Cak AT: Politik 'Kayyum' ala Turki
Dalam konteks pendidikan modern, penerapan asesmen yang ilmiah, akademis, dan valid menjadi sangat penting untuk memahami potensi dan kecenderungan belajar setiap siswa. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah asesmen Multiple Intelligence (MI) yang diperkenalkan oleh Howard Gardner.
Asesmen ini mengidentifikasi sembilan jenis kecerdasan: logis-matematis, musikal, visual-spasial, kinestetik, verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, eksistensial, hingga naturalis.
Melalui instrumen sederhana seperti kuisioner MI atau observasi yang terstruktur, guru dapat mengenali kekuatan siswa secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif tradisional.
Meski pada awalnya tampak kompleks, asesmen ini dapat diterapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan konteks lokal sekolah, asalkan dilakukan dengan konsistensi dan didukung pelatihan yang memadai.
Baca juga: Artis Paula Verhoeven Terbukti Selingkuh, Tidak Berhak Terima Nafkah
Manfaat dari asesmen seperti ini sangat besar. Selain membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang lebih personal, hasilnya juga bisa menjadi dasar penguatan keterampilan kolaboratif siswa. Di era saat ini, seseorang tidak bisa lagi mengandalkan satu jenis kecerdasan atau keahlian saja.
Dunia kerja dan dunia usaha menuntut kolaborasi lintas keahlian. Dalam membangun sebuah produk, misalnya, dibutuhkan seorang ahli bahasa untuk menyusun narasi promosi, seorang ahli ekonomi untuk merancang strategi pemasaran, dan seorang teknisi untuk memastikan efisiensi produk.
Dengan mengenali tipe kecerdasan masing-masing siswa sejak dini, guru bisa mengarahkan mereka pada peran-peran yang sesuai dalam kerja tim. Asesmen menjadi alat penting untuk membentuk generasi yang tak hanya cerdas secara individu, tetapi juga siap bekerja sama dan berkontribusi secara kolektif.
Namun, begitulah. Selama ini, penjurusan dipilih bukan selaras dengan bakat atau minat siswa, yang memang belum sanggup kita petakan secara akademis, tapi lebih dipilih karena mitos dan tekanan sosial. Di sini kita bisa bertanya, sekolah itu tempat belajar atau tempat stigma dilegalisasi?
Baca juga: Catatan Cak AT: Ayat Tanah di Lingkar Kuasa Oligarki
Kembalinya penjurusan akan menghidupkan lagi monster lama: jurusan sebagai kasta. IPA di atas, IPS di bawah, Bahasa entah di mana—mungkin di ruang UKS karena sering sakit hati.
Padahal, dunia kerja dan kehidupan tidak lagi mengkotak-kotakkan kemampuan manusia seketat itu. Kita sedang hidup di zaman ketika anak IPS bisa jadi data scientist, anak Bahasa jadi diplomat, dan anak IPA jadi seleb TikTok.
Tapi logika penjurusan tetap seperti tahun 90-an: IPA itu pintar, IPS itu cerewet, Bahasa itu... pilihan terakhir.
Dan dari mana kita bisa mengenali minat dan bakat siswa? Dari nilai UN? Dari omongan wali kelas yang baru ketemu mereka dua bulan? Atau dari keinginan orang tua yang ingin anaknya "jangan kayak Bapak, ya"?
Baca juga: Belanda Dukung Rencana Depok Lama Jadi Kawasan Heritage, Lestarikan Warisan Budaya
Tanpa asesmen yang valid dan terstruktur, kita hanya memindahkan kebingungan siswa dari sistem terbuka ke dalam sangkar sistem tertutup.
Di berbagai negara maju seperti Jerman, Belanda, Jepang, China, dan Korea Selatan, sistem pendidikan mereka telah lama mengintegrasikan asesmen dan penjurusan sejak usia sekolah menengah.
Di Jerman dan Belanda, misalnya, siswa mulai diarahkan ke jalur akademik atau vokasional berdasarkan asesmen kemampuan dan minat yang dilakukan secara sistematis.
Jepang dan Korea Selatan, meski dikenal sangat kompetitif, mulai menggeser pendekatannya ke arah yang lebih fleksibel dengan memberikan ruang untuk asesmen berbasis minat dan kepribadian.
Baca juga: Darurat Sampah, DPRD Depok Dorong Pemerintah Gandeng Pihak Ketiga
China pun telah mengadopsi berbagai asesmen modern untuk memetakan potensi siswa sejak dini, seiring dengan tuntutan industri yang terus berkembang.
Penjurusan yang berbasis asesmen ini memungkinkan siswa berkembang sesuai kekuatan unik mereka, sekaligus mempersiapkan mereka untuk berperan dalam masyarakat yang semakin menuntut kolaborasi lintas bidang.
Kita tak menolak struktur. Yang kita tolak adalah struktur yang malas. Kita tidak anti-penjurusan, tapi anti pengkotak-kotakan.
Jika memang siswa butuh kerangka, mari kita sediakan. Tapi pastikan kerangka itu bisa lentur, bukan seperti korset ibu-ibu zaman Belanda yang membuat napas susah, apalagi berpikir jernih.
Baca juga: Catatan Cak AT: Jalan Berliku Upaya Mengadili Sang Mantan
Penjurusan seharusnya jadi alat bantu, bukan palu godam. Kalau perlu, gabungkan pendekatan lintas minat: anak IPA bisa ambil sosiologi, anak IPS bisa ngintip matematika. Dunia ini tak sehitam-putih worksheet LKS.
Akhir kata, mari hormati kacang yang belum tumbuh. Siswa SMA itu masih mencari diri. Mereka belum tahu apakah mereka suka ekonomi atau fisika, novelis atau neurolog.
Dan yang paling tahu tentang mereka... sebenarnya bukan kita, bukan guru, bukan orang tua—tapi asesmen yang objektif. Jadi, mari kita beri mereka peta sebelum memaksa mereka memilih jalan.
Menghidupkan kembali penjurusan tanpa reformasi sistem bimbingan dan asesmen sama saja dengan menyuruh anak panjat tebing tanpa tali. Seru sih, tapi yang jatuh lebih banyak dari yang sampai puncak.
Baca juga: UI Lakukan Skrining Kesehatan dan Edukasi Pencegahan Stunting di Kepulauan Seribu
Mari kita suarakan penolakan pada penjurusan dan pengkotak-kotakan. Bukan karena anti masa lalu, tapi karena kita ingin masa depan yang lebih berpihak pada potensi anak.
Karena kita tahu, pendidikan bukan soal kotak, tapi tentang membuka jalan. Dan jalan itu tak selalu lurus. Kadang harus melingkar, menanjak, bahkan kembali ke titik awal —asal tidak tersesat karena kompasnya rusak. (***)
Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 21/4/2025


 Bisnis - 17 Oct 2025
Bisnis - 17 Oct 2025




