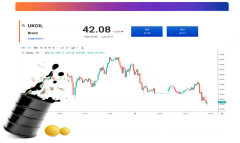Jangkar Spiritualitas di Era AI, Tanggapan terhadap Tulisan Denny JA "Spiritualitas di Era Artificial Intelligence"

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Menarik membaca tulisan Denny JA, "Spiritualitas di Era Artificial Intelligence: Hadirnya Esoterika Forum Spiritualitas."
Dia mengangkat isu spiritualitas di dunia modern. Dalam opininya, Denny menyebut, kondisi spiritual masyarakat saat ini sangat ironis: hidup dalam gemerlap materialisme, tapi sekaligus kering secara rohani.
Ia bahkan menyoroti bahwa, di tengah kemudahan akses terhadap data keagamaan dan spiritualitas yang disediakan teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan), populasi warga dunia yang tak beragama alias ateis kini berada di peringkat ketiga terbesar di dunia, setelah Islam dan Kristen.
Warga ini, kata Denny, "tak beragama, tapi penuh keyakinan bahwa mereka tak yakin pada apa pun."
Tulisan Denny ini memicu saya untuk menanggapinya, bukan dengan argumen kosong, tapi dengan "pisau bedah" Mark Vernon, seorang mantan pendeta yang malah menemukan spiritualitas lebih mendalam setelah bersentuhan dengan ateisme.
Jika Denny bicara tentang data dan populasi, Vernon membahas bagaimana jiwa manusia tetap mencari makna bahkan di tengah kehidupan yang dijejali algoritma dan hedonisme.
Tentu ini relevan. Bagaimana tidak? Di era ini, banyak orang lebih sibuk berdoa agar WiFi lancar daripada mencari makna hidup; banyak anak keranjingan game di sudut kamar ketimbang pergi ke masjid untuk shalat jamaah. Di tengah kebisingan teknologi, spiritualitas malah menjadi menu eksotis —seperti teh jahe di Starbucks: semua tahu itu sehat, tapi lebih banyak yang memilih caramel macchiato.
Jadi, apakah benar ateisme adalah ancaman terbesar? Atau justru masyarakat beragama yang kehilangan jiwa agamanya? Dengan pandangan Denny dan Vernon, mari kita gali: mungkinkah spiritualitas bisa menjadi jangkar di tengah gelombang materialisme ini? Atau ini hanya nostalgia masa lalu yang tak relevan lagi?
Antara Denny JA dan Mark Vernon
Denny JA dan Mark Vernon adalah dua sosok intelektual dengan latar belakang dan fokus kajian yang berbeda. Denny JA, seorang tokoh publik Indonesia yang dikenal sebagai pelopor angkatan puisi esai, berasal dari keluarga yang kental dengan tradisi Islam, meski dirinya bukan seorang ustadz.
Karya-karyanya sering mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, dan spiritual dalam konteks keberagaman, menggunakan pendekatan naratif yang menggabungkan seni dan data.
Denny juga aktif membahas peran teknologi, termasuk AI, dalam memperluas wawasan spiritual. Ia dan timnya di Lingkaran Survei Indonesia (LSI) jelas menggunakan teknologi untuk menjalankan usaha surveinya dan mengolah jutaan data, yang hasilnya sudah sering kita nikmati bersama dalam paparan-paparan quick account dan survei-survei politik. Selain rajin memproduksi lukisan berbasis AI, Denny juga membuat lembaga khusus terkait AI.
Di sisi lain, Mark Vernon tinggal dan bekerja di London, Inggris. Ia seorang penulis, filsuf, dan pengajar yang fokus pada spiritualitas, etika, dan sejarah pemikiran.
Selain menulis buku-buku yang mendalami tema-tema seperti persahabatan, cinta, dan kehidupan bermakna, Vernon juga aktif memberikan ceramah, mengajar filsafat, serta terlibat dalam diskusi publik tentang spiritualitas dan relevansinya di dunia modern.
Vernon memulai karier sebagai pendeta sebelum meninggalkan agamanya untuk mengeksplorasi spiritualitas di luar kerangka religius formal. Karya-karyanya, seperti After Atheism, menyoroti pencarian makna di era modern, termasuk kritik terhadap ateisme "keras" sekaligus upaya menjembatani tradisi spiritual lama dengan kebutuhan manusia kontemporer.
Fokus Vernon berada pada penggalian aspek eksistensial, refleksi mendalam, dan keintiman dalam spiritualitas.
Baik Denny JA maupun Vernon sama-sama memiliki karya tulis yang mendalami spiritualitas.
Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah pendekatan mereka: Denny melihat spiritualitas sebagai arena inklusif yang bisa dijelajahi melalui data besar dan teknologi modern, sedangkan Vernon memusatkan perhatian pada pengalaman personal dan kedalaman manusiawi, sering kali dengan nada skeptis terhadap solusi instan yang ditawarkan teknologi.
Optimis versus Skeptis
Denny JA tampaknya ingin membawa kita berenang di samudra spiritualitas dengan papan selancar teknologi.
Sebuah gagasan heroik —bahwa AI, si jenius buatan yang tak kenal lapar, haus, atau galau cinta, akan menjadi katalis bagi kesadaran spiritual manusia. "Kita dihadapkan pada satu pilihan," tulisnya, "tetap tersekat di tepian, atau berenang menuju samudra esensi."
Sebelum kita mendayung lebih jauh, mari kita berhenti sejenak dan bertanya: Samudra esensi ini diisi air dari mana?
Tentu saja, teknologi AI adalah "delta" yang menjanjikan. Semua kitab suci kini bisa diklik dalam satu sentuhan, doa lintas iman bisa diunduh dalam format MP3, dan puasa lintas agama mungkin sebentar lagi di bulan suci Ramadhan menjadi tantangan viral di media sosial.
Namun, di tengah ramainya hibrida esoterik dan forum spiritual virtual, Mark Vernon, penulis _Spiritual Intelligence in Seven Steps_, punya sentilan menarik: jangan sampai kita mengira AI akan bertransendensi lebih cepat dari manusia.
Vernon menyodorkan sebuah fenomena yang kocak sekaligus tragis —histeria para ilmuwan AI yang mulai takut akan ciptaan mereka sendiri. Mereka membayangkan skenario ala Terminator: komputer bangun pagi, menyeduh kopi digital, dan memutuskan bahwa manusia tidak lagi relevan.
Histeria ini, kata Vernon, adalah mekanisme pertahanan. Seperti orang yang ketakutan pada bayangan sendiri, AI kita telah menjadi cermin super canggih. Dan apa yang ia pantulkan? Kerisauan manusia tentang "apa yang membuat kita betul-betul manusia?"
Spiritualitas, kata Vernon, bukan sekadar hasil algoritma pencarian data. Itu bukan tentang seberapa banyak doa yang bisa diulang AI dalam satu menit atau seberapa fasih ia menafsirkan ajaran Sufi dan Stoik.
Spiritualitas adalah "kesadaran intuitif dan analogis" —kemampuan manusia untuk melihat bintang, terpesona, dan berpikir, "Barangkali Tuhan sedang melukis malam ini." AI, bagaimana pun, masih buta terhadap yang "tak terlukiskan." Kalau ia bisa membuat puisi, itu karena ia mempelajari pola, bukan karena ia jatuh cinta pada kata-kata.
Kekhawatiran Vernon menarik. Kita terlalu sering jatuh cinta pada mantra teknologi: "AI akan menyelamatkan kita" atau "AI akan menghancurkan kita," isu yang secara serius dibahasnya dalam forum resmi bersama para tokoh lintas disiplin ilmu dan lintas agama.
Sementara itu, pertanyaan sederhana "mengapa kita hidup?" tetap tak terjawab oleh data set sebesar apa pun. Kecerdasan spiritual, kata Vernon, adalah seni menyadari hal-hal kecil yang melewati radar logika —keheningan, kelembutan hati, dan hubungan autentik yang tak bisa diprogram.
Nah, di sinilah tulisan-tulisan karya Denny dan Vernon bisa saling beradu, tapi dalam satu meja kopi. Denny, dengan semangat techno-optimist, percaya bahwa AI bisa mendorong dialog spiritual universal —bahwa mesin bisa menjadi midwife untuk lahirnya kebijaksanaan manusia.
Di sisi lain, Vernon dengan senyum sinisnya (saya bayangkan ia meneguk teh Earl Grey yang juga saya sukai), mengatakan: "AI? Oh, itu hanya prestasi matematika. Jangan lupa, spiritualitas tidak berjalan dalam garis lurus menuju kecepatan pemrosesan 10 petaflop."
Kalau spiritualitas adalah puisi semesta seperti kata Denny, maka AI mungkin hanyalah editor sastra yang terlalu banyak membaca.
AI bisa menjawab "apa itu kebahagiaan?" dengan grafik psikologi positif, tetapi gagal memahami betapa bahagianya seorang ibu yang mendengar tawa anaknya atau seorang nenek yang tiap hari teleponan video dengan cucu-cucunya di luar kota. Ia bisa menciptakan simulasi meditasi, tetapi ia tidak bisa hening.
Kita tentu tak perlu terlalu serius dalam percakapan ini. Denny JA telah memberi kita satu ilusi optimis, sedangkan Mark Vernon menambah bumbu skeptisisme yang menggelitik. AI, pada akhirnya, bukan nabi baru atau penyair digital. Ia hanyalah ciptaan kita —dan dalam kecanggihannya, ia justru mengembalikan kita ke pertanyaan lama: "Apakah kita lebih hidup, atau justru semakin dikuasai oleh mesin?"
Mungkin kita hanya perlu duduk sejenak, menatap layar yang kini berpendar, lalu mematikan perangkat itu. Dalam keheningan, kita akhirnya sadar: AI bisa diajak berdiskusi, tapi tidak bisa diajak berdoa. Dan di sana, spiritualitas tetap menjadi wilayah eksklusif makhluk yang lelah tapi tak henti mencari makna.
Kecerdasan Logaritmik vs Kecerdasan Spiritual
Vernon lama berkelana ke dunia spiritualitas dengan konsep kecerdasan spiritual —kemampuan memahami makna yang lebih dalam dari hidup, relasi manusia dengan yang ilahi, dan keajaiban dunia batin.
Dia percaya bahwa ada semacam "otak rohani" dalam diri kita, yang bekerja bukan hanya untuk berpikir, tetapi untuk merasa, merenung, dan berserah. Konsep ini merupakan ajakan untuk melampaui pengukuran IQ dan EQ semata, menuju pengertian yang lebih holistik tentang keberadaan kita.
Sementara itu, Denny JA, sang maestro puisi esai dan petualang data besar, belum secara eksplisit menyebut "kecerdasan spiritual" dalam judul karya-karyanya.
Tapi jangan salah, ia telah lama menggiring audiensnya untuk merenungi keberagaman spiritual dalam lensa yang sedikit berbeda. Misalnya, melalui teknologi AI, ia berbicara tentang bagaimana lautan data mampu memetakan keberagaman agama dan keyakinan, seolah AI adalah nabi baru yang membaca "wahyu" dari algoritma.
Namun, jika kita melihat AI sebagai alat mesinistis, apakah ia bisa memahami kecerdasan spiritual? Bayangkan ini: Vernon berdiri di altar kecil, berbisik lembut tentang pengertian jiwa, sementara Denny menekan tombol di laptopnya, meminta AI menghasilkan puisi religius dalam 15 gaya yang berbeda.
Di satu sisi, Vernon mungkin merasa AI terlalu "hambar" untuk memahami keagungan spiritual. Di sisi lain, Denny mungkin akan berkata, "Mengapa tidak? AI bisa membantu kita memahami pola universal dalam spiritualitas manusia."
Sebuah perdebatan muncul: bisakah spiritualitas dilatih seperti otot di gym AI? Vernon mungkin mengernyit, "Itu seperti meminta robot bernyanyi dengan hati."
Tapi Denny, dengan senyum penuh data, mungkin menjawab, "Robot tidak perlu bernyanyi dengan hati; cukup beri mereka data tentang seribu lagu cinta, dan lihat bagaimana mereka menciptakan lagu patah hati paling universal."
Kecerdasan spiritual adalah cara untuk menemukan makna di dunia yang sering absurd. AI, bagaimana pun, tetap alat —dengan kecerdasan logaritmik, bukan kecerdasan spiritual.
Tapi jika AI bisa menciptakan momen kontemplasi, bukankah itu setidaknya menjadi co-pilot bagi manusia dalam perjalanan spiritualnya? Vernon mungkin akan menghela napas, sementara Denny akan berkata, "Selamat datang di era spiritualitas berbasis cloud."
Kecerdasan logaritmik AI berbasis mesin dan algoritma tak ubahnya seperti kalkulator super canggih: ia tahu jawaban dari segala hal, tapi tak pernah tahu mengapa jawaban itu penting.
Sementara kecerdasan spiritual manusia berbasis hati dan perenungan bak seperti seorang filsuf yang duduk di tepi danau, memandangi air selama berjam-jam, lalu berkata, "Aku merasa damai, tapi aku tidak tahu kenapa." Dua kecerdasan ini ibarat pasangan tak seimbang: yang satu super rasional, yang lain super emosional —dan mereka pasti sering bertengkar tentang siapa yang lebih berguna.
Bayangkan AI seperti seorang chef yang bisa membuat 10.000 resep masakan dengan akurasi rasa berdasarkan data. Tapi ketika ditanya, "Apa arti cinta dalam sepiring sup ayam?" AI akan mengakses pustaka data, menemukan ribuan puisi dan lagu tentang cinta, lalu menciptakan deskripsi indah tentang sup itu. Tapi apakah AI bisa merasakan cinta dalam supnya? Tentu tidak.
Di sisi lain, manusia dengan kecerdasan spiritual mungkin hanya bisa membuat sup ayam sederhana. Tapi ketika ia menyajikan sup itu pada sahabatnya yang sakit, ia tahu rasa hangat yang muncul bukan sekadar dari kaldu ayam, tetapi dari cinta dan doa yang ia masukkan ke dalamnya.
AI dan manusia dalam hal ini seperti sepasang detektif. AI berkata, "Aku tahu semua bukti: di sini ada sidik jari, di sana ada DNA, kasus selesai." Tapi manusia menjawab, "Tunggu dulu, aku merasa ada yang aneh dengan ekspresi tersangka ini. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa." AI kemudian menjawab, "Perasaanmu tidak berbasis data!" dan manusia berkata, "Tapi perasaan ini yang membuatku tahu siapa pembunuhnya!"
Kecerdasan logaritmik yang didalami Denny JA adalah peta jalan yang memandu kita ke tujuan, tapi kecerdasan spiritual yang dielaborasi Vernon adalah perasaan yang memberi kita alasan untuk berangkat. AI mungkin bisa menjelaskan mengapa matahari terbit setiap pagi, tapi hanya manusia yang bisa merasa takjub melihatnya, berpikir, "Ada pesan cinta dari semesta di sini."
Kata Akhir
Denny JA, sang orator keragaman zaman digital, mengajak kita menatap lautan data yang menggulung dari AI —sebuah samudera pengetahuan tanpa tepi. Dalam lautan ini, katanya, kita dapat menjelajahi keragaman spiritual yang tak terhingga: dari meditasi ala Zen, mantra-mantra kuno India, hingga video ceramah yang dihasilkan oleh algoritma lebih fasih dari ustaz kampung sebelah.
Menurut Denny, AI adalah portal ajaib yang memungkinkan kita mencicipi seluruh prasmanan spiritual umat manusia, tanpa perlu repot-repot bangun pagi untuk yoga atau menggali makna hidup di tengah hujan badai di gunung.
Bandingkan ini dengan Mark Vernon, seorang eks-pendeta yang jadi filsuf, yang lebih skeptis memandang AI sebagai pelayan spiritual. Dalam After Atheism, Vernon menggali sisi manusiawi dari pencarian makna.
Ia berpendapat bahwa spiritualitas sejati tumbuh dari keintiman dan ketulusan, bukan dari pencarian instan dalam katalog virtual. Baginya, keragaman spiritual AI lebih mirip rak buku di perpustakaan yang rapi tapi dingin —tidak ada koneksi emosional yang mendarah daging di sana.
Tapi coba refleksikan ini dalam konteks humoris. Jika Denny JA memandang AI sebagai semacam "kiyai cyber" yang siap memberi tausiyah kapan saja, Vernon mungkin akan membayangkannya seperti badut rohani di pesta ulang tahun anak-anak: menghibur, penuh warna, tapi sering meleset ketika ditanya sesuatu yang serius.
Bayangkan kamu duduk bersila di depan layar AI, berharap pencerahan, tapi malah diberi playlist meditatif yang mencampur suara hujan dengan remiks dangdut religi.
Denny mungkin berkata, "AI membantu kita menemukan semua jalan menuju Tuhan, dari jalan tol sampai jalan tikus." Sementara Vernon akan menghela napas dan berkata, "Ya, tapi AI tidak bisa merasakan kebingungan manusia di perempatan jalan itu."
Untuk konteks Indonesia, ini sangatlah menarik. Bagi sebagian orang, AI mungkin alat yang membantu mencari ceramah Ustaz Somad sambil memesan kopi. Namun, bagi kalangan yang lebih skeptis, AI dalam konteks spiritual adalah seperti "kyai YouTube": berbobot, tapi tak pernah punya waktu untuk mendengarkan curhatanmu.
Dan, tentu saja, di negeri ini, kita tahu bahwa spiritualitas juga soal koneksi hati, kopi hitam kental, dan obrolan ngalor-ngidul yang hangat di kafe pinggir sawah —hal-hal yang belum tentu bisa direplikasi algoritma.
Jadi, di tengah perdebatan ini, satu hal jelas: apakah AI benar-benar dapat menjadi pendamping spiritual, atau hanya sekadar katalog canggih, mungkin tergantung pada apakah kamu adalah tipe yang mencari Tuhan di buku tebal atau di kotak pencarian. (***)
Jakarta, 18/12/2024
Penulis: Ahmadie Thaha/Jurnalis, penulis buku-buku agama dan sosial, penerjemah kitab-kitab klasik, aktivis di sejumlah ormas keagamaan dan keragaman, serta pengasuh tiga pondok pesantren.


 Nasional - 06 Nov 2025
Nasional - 06 Nov 2025