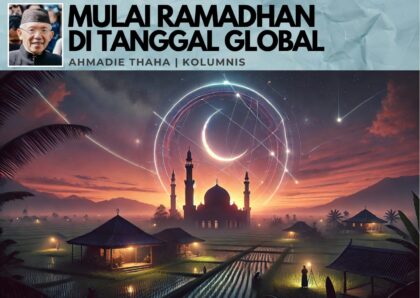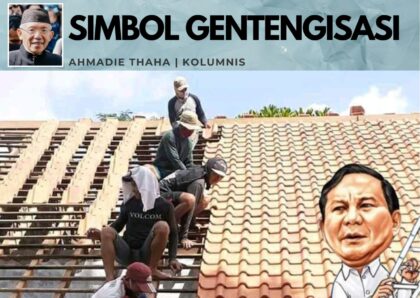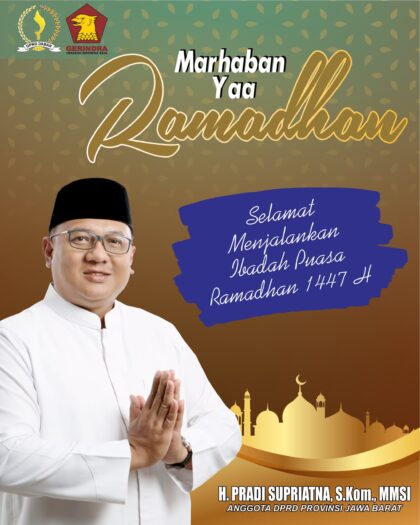RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Ada pepatah lama yang tidak tercatat di prasasti manapun tapi hidup di mulut rakyat: Titah raja bisa jadi agama.
Di Bali, ini bukan sekadar metafora —ia menjelma dalam bentuk selembar kain berwarna-warni yang kini merayap ke setiap tubuh, dari ASN sampai anak SD. Namanya Endek. Kitab sucinya? Surat edaran. Hari rayanya? Setiap Selasa.
Jangan heran kalau sekarang Bali seperti sedang menggelar “haji kecil” kain. Semua orang berbondong-bondong menjadi jamaah endek, dengan motif bunga, garis, bahkan motif-motif yang entah filosofinya apa tapi katanya “mengandung makna mendalam”.
Kalau ditanya maknanya, banyak yang tersenyum kecut sambil bilang, “Pokoknya ini motif Karangasem, bro.”
Baca juga: Naturalisasi Anak Depok Sebentar Lagi Final, Siap Bertarung di Round 4 Piala Dunia
Dulu, endek dianggap kain yang agak kudet: mahal, panas, kaku, bahkan “ndeso”. Tapi sejak Gubernur Wayan Koster mengeluarkan titah wajib endek tiap Selasa untuk ASN, pejabat, sampai pelajar, sikap publik berubah drastis.
Kini siapa yang tak punya endek, ia bagaikan orang Bali yang tak pernah makan lawar —aneh dan memalukan.
Di sinilah saya perlu mengutip catatan lapangan Wayan Suyadnya, yang suatu hari iseng jalan di Denpasar dan menemukan butik-butik endek bermunculan di mana-mana: Jalan Kemuda, Seroja, Nangka, Antasura, Kenyeri, hingga Padma.
Pemiliknya orang Bali sendiri, menghidupkan kembali perajin udeng dan penjahit lokal yang sempat “tertidur” karena serbuan pakaian instan pabrik. Fenomena ini, kata Wayan, mengubah wajah jalanan Bali —dari yang dulu penuh jaket dan celana jeans, kini jadi pawai kain adat setiap pekan.
Baca juga: 80 Tahun Kemerdekaan, Lapangan Pekerjaan untuk Semua Topang Pilar Indonesia Emas 2045
Lalu, mari kita bicara soal fakta. Endek bukan kain instan seperti kaos distro. Ia dibuat dengan teknik ikat pakan (weft ikat), motif diikat, benang dicelup berkali-kali, lalu ditenun manual dengan ATBM (alat tenun bukan mesin). Satu lembar bisa makan waktu sebulan. Wajar kalau harga mulai dari Rp120 ribu per meter, hingga jutaan untuk sutra motif eksklusif. Kalau mau gaya, ongkos jahitnya bisa nyaris separuh harga kainnya.
Masalahnya, di balik euforia ini, ada potensi jebakan. Pertama, inflasi gengsi: kain Rp500 ribu dijual sejuta hanya demi “branding” butik. Kedua, banjir imitasi: endek “made in pabrik” yang dicetak, bukan ditenun, mulai merembes ke pasar. Ketiga, seragamisasi rasa: ketika semua orang diwajibkan memakai, ekspresi personal bisa hilang, dan endek jadi sekadar “pakaian dinas” alih-alih karya budaya.
Di titik ini, saya tak ingin menjadi pengkhotbah di pojok pasar. Justru saya ingin kebijakan ini bertahan, tapi dengan akal sehat. Kalau pemerintah bisa bikin aturan wajib endek, mestinya bisa juga bikin lembaga kurator mutu.
Baca juga: Teater Sastra UI Alumni UI Lintas Generasi akan Persembahkan Malam Dzikir Puisi
Setiap butik yang lulus pembinaan mendapat sertifikat resmi, seperti label halal di warung bakso. Dan setiap kain disertai narasi —“Ditenun oleh Bude Keling, benang dari kapas Blahbatuh, motif warisan abad ke-17”— supaya pembeli merasa membeli cerita, bukan sekadar tekstil.
Karena tanpa itu, kita bisa terjebak dalam cinta yang sementara. Hari ini kita bangga, besok kita jengkel karena kain yang kita beli pudar setelah dua kali cuci. Pasar rakus bisa membunuh romansa secepat ia menenunnya.
Dan jangan lupa, Bali bukan satu-satunya pulau yang punya motif di benangnya dan kisah di kainnya. Dari Aceh sampai Papua, tiap daerah punya “endek”-nya sendiri —entah namanya ulos, songket, tapis, sasirangan, atau koteka (yang, mohon maaf, fungsi utamanya agak berbeda).
Indonesia ini bisa “bhinneka” bukan cuma karena kita hafal lirik lagu kebangsaan, tapi karena tiap daerah punya budaya yang bisa dihidupkan seperti Bali menghidupkan endek.
Baca juga: Catatan Cak AT: Panggung Dunia eSport di Riyadh
Coba bayangkan kalau tiap provinsi berani mengangkat warisan kainnya sendiri seperti ini —bukan hanya jadi dekorasi di ruang tamu gubernur, tapi menempel di badan warganya. Kita bisa punya parade busana nasional sepanjang tahun, tanpa harus menunggu karnaval 17 Agustusan seperti hari ini.
Akhir kata, fenomena ini adalah paradoks yang layak dicatat: kebijakan yang awalnya dipandang merepotkan, bahkan ditolak, kini menjadi simbol kebanggaan kolektif.
Endek telah naik pangkat: dari kain yang dipakai karena terpaksa, menjadi bahasa identitas yang disampaikan Bali kepada dunia. Bedanya, bahasa ini tidak diucapkan lewat kata, melainkan lewat motif dan warna di punggung para penunggang motor setiap Selasa pagi. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 17/8/2025