RUZKA INDONESIA — Setiap tahun, kemiskinan datang dengan kabar yang terdengar menggembirakan. Angkanya turun, persentasenya membaik, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan disebut terkendali.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Jawa Barat tahun 2025 mencatat penduduk miskin sebesar 2,31 persen atau sekitar 63 ribu jiwa. Di atas kertas, ini adalah prestasi. Namun di kehidupan nyata, pertanyaannya sederhana dan mengusik: mengapa rasa “tidak miskin” itu tak kunjung sampai ke perut warga?
Kemiskinan hari ini bukan lagi sekadar persoalan angka. Ia adalah soal jarak antara statistik dan realitas. Ketika kemiskinan diumumkan menurun, warga justru berhadapan dengan harga beras yang naik, biaya kontrakan yang kian mencekik, ongkos transportasi yang terus bertambah, dan kebutuhan dasar yang tak pernah benar-benar murah.
Di sinilah kemiskinan menjadi paradoks: menyusut dalam laporan, membesar dalam kehidupan sehari-hari.
Garis kemiskinan Kota Depok tahun 2025 berada di kisaran Rp884.663 per kapita per bulan. Angka ini menjadi batas formal siapa yang dikategorikan miskin dan siapa yang tidak. Masalahnya, batas ini lebih mencerminkan standar bertahan hidup daripada standar hidup layak.

Dengan biaya hidup perkotaan yang tinggi, seseorang yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan sejatinya masih berada di wilayah rawan. Ia tidak miskin secara statistik, tetapi jauh dari sejahtera secara faktual.
Di titik inilah kita perlu jujur mengakui bahwa kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan, melainkan soal daya hidup. Banyak warga bekerja, bahkan bekerja keras, namun tetap terjebak dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Mereka tidak tercatat sebagai penduduk miskin, tetapi hidup dalam ketidakpastian. Sedikit guncangan—sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga pangan—cukup untuk menjatuhkan mereka ke jurang kemiskinan.
Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sering dijadikan bukti bahwa kondisi penduduk miskin semakin membaik. Secara teknis, ini berarti pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka relatif stabil.
Namun indikator ini kerap gagal menangkap satu hal penting: kerentanan struktural. Kemiskinan hari ini tidak selalu tampak ekstrem, tetapi ia tersebar luas dalam bentuk kehidupan yang pas-pasan dan tanpa jaring pengaman yang kuat.
Narasi penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu dikritisi secara jernih. Kemiskinan ekstrem memang harus ditangani, tetapi menjadikannya sebagai satu-satunya fokus berisiko melahirkan kepuasan semu. Ketika kemiskinan ekstrem dianggap selesai, negara seolah boleh menarik napas lega, padahal sebagian besar warga miskin dan rentan masih berkutat pada masalah yang sama: penghasilan tak stabil, akses layanan terbatas, dan minimnya perlindungan sosial.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini masih terlalu bertumpu pada bantuan sosial. Bantuan memang penting sebagai penyangga, tetapi ia sering berhenti sebagai solusi jangka pendek. Bantuan mencegah warga jatuh lebih dalam, namun jarang benar-benar mendorong mereka naik kelas. Tanpa strategi pemberdayaan yang berkelanjutan, kemiskinan hanya berpindah bentuk, bukan benar-benar berkurang.
Lebih dari itu, kemiskinan kerap diperlakukan sebagai persoalan teknokratis. Ia direduksi menjadi tabel, grafik, dan persentase, kehilangan wajah manusianya. Padahal kemiskinan adalah cerita tentang keluarga yang menunda berobat karena tak punya biaya, anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, dan pekerja informal yang hidup tanpa kepastian hari esok. Ketika kemiskinan hanya dibaca dari laporan, empati perlahan menghilang.
Sebagai kota penyangga ibu kota, Depok menghadapi tantangan khas perkotaan. Biaya hidup tinggi, persaingan kerja ketat, dan sektor informal yang mendominasi membuat kemiskinan di kota sering kali tersembunyi. Ia tidak selalu hadir dalam wajah kumuh, tetapi bersembunyi di rumah petak, kontrakan sempit, atau kos-kosan padat. Warganya bekerja, namun penghasilannya tidak pernah cukup untuk benar-benar hidup layak.
Karena itu, penurunan jumlah penduduk miskin seharusnya tidak membuat kita cepat puas. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa orang yang keluar dari statistik kemiskinan, tetapi dari seberapa banyak warga yang benar-benar memiliki masa depan yang lebih baik. Jika warga masih hidup dalam kecemasan ekonomi, maka klaim keberhasilan itu patut dipertanyakan.
Data tetap penting sebagai dasar kebijakan. Namun data tanpa keberpihakan hanya akan melahirkan kebijakan yang dingin. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membaca data secara kritis dan menjadikannya alat perubahan, bukan sekadar alat legitimasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menurunkan angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.
Pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar tentang siapa yang tercatat miskin, melainkan siapa yang hidup tanpa kepastian. Jika penurunan kemiskinan hanya berhenti di atas kertas, maka ia tak lebih dari kemenangan administratif. Pembangunan seharusnya membuat warga merasa hidupnya membaik, bukan sekadar terlihat membaik dalam laporan.
Jika kemiskinan sungguh ingin dihapus, maka yang harus dikurangi bukan hanya angkanya, tetapi juga ketimpangan, kerentanan, dan ketidakpedulian. Tanpa itu, penduduk miskin Kota Depok 2025 akan terus “turun” di data, namun tetap bertahan di meja makan yang kosong.
Dan di sanalah ironi pembangunan kita hari ini berdiri. (***)
Penulis: Djoni Satria


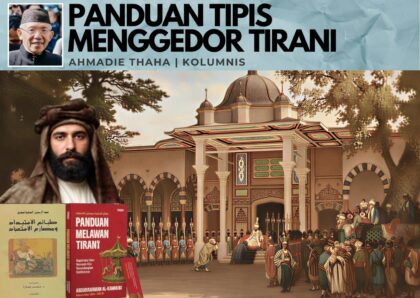



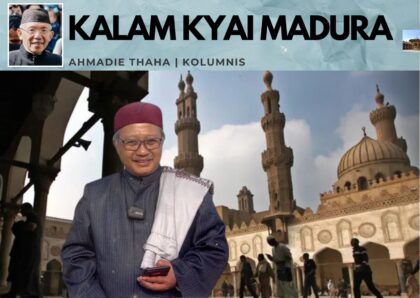

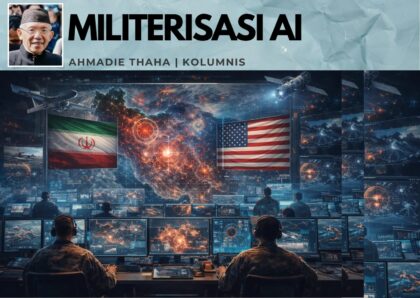












Komentar