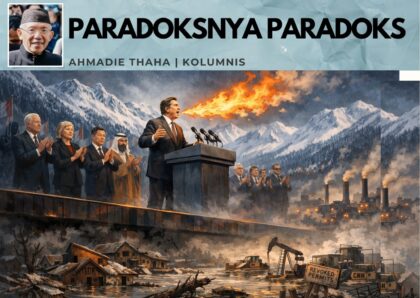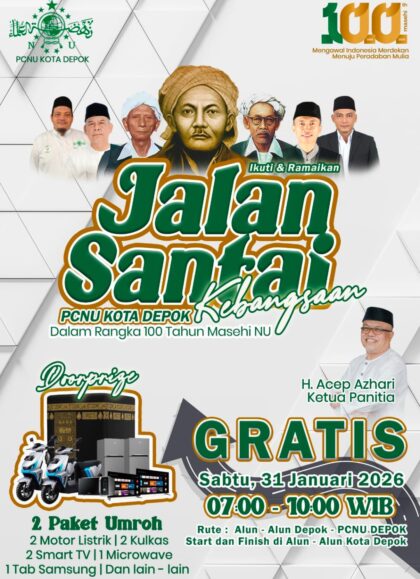RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Ada satu hal yang lebih menakutkan dari suara hujan yang tak kunjung reda, lebih menyesakkan dari sungai yang tiba-tiba berubah menjadi jalan raya yang mengamuk, lebih mengerikan dari retakan tanah yang merenggut rumah dan manusia sekaligus: ketidakpekaan kita sendiri.
Ketika banjir dan longsor besar di Sumatera minggu ini merenggut 442 jiwa, ketika 402 orang masih hilang, ketika ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian, kita—sebagai bangsa—terasa semakin terbiasa.
Seolah tragedi bukan lagi peristiwa luar biasa, tetapi bagian dari kalender bulanan yang hanya menunggu gilirannya.
Dan ketika bencana tak lagi mengejutkan kita, itulah bencana yang paling besar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dalam konferensi pers di Pos Pendukung Nasional, Bandara Silangit, Tapanuli Utara (30/11/2025), menyampaikan data yang seharusnya membuat tubuh ini merinding: 442 orang meninggal dunia, 402 hilang, dan puluhan ribu mengungsi di tiga provinsi—Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Mari kita tidak buru-buru melewati angka-angka itu. Mari kita duduk sejenak dan merasakannya.
Empat ratus empat puluh dua jiwa. Itu bukan angka statistik. Itu adalah nama, wajah, cita-cita, foto keluarga, suara, dan doa-doa yang tak sempat terkabul.
Di Sumatra Utara, korban jiwa mencapai 217 orang, sementara 209 lainnya hilang, dan 16 luka-luka. Angka itu tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
Sementara itu, pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.
Sebagian daerah masih terisolasi total. Jalan Tarutung–Sibolga terputus di banyak titik; alat berat baru bisa menembus 40 kilometer, sementara lebih dari 12.000 jiwa di Tapanuli Utara masih menunggu pertolongan—menunggu dengan perut lapar, dengan dingin malam, dengan kecemasan apakah keluarga mereka selamat.
Di Sumatra Barat, catatan duka tak kalah dalam: 129 meninggal dunia, 118 hilang, dan 77.918 jiwa mengungsi. Kota Padang, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan—daerah-daerah yang selama ini kita kenal karena keelokan alamnya—hari ini menjadi saksi bisu dari amukan cuaca ekstrem dan rentannya daya dukung lingkungan.
Sementara di Aceh, provinsi yang berkali-kali diguncang bencana besar sepanjang sejarahnya, tercatat 96 korban jiwa dan 75 hilang. Tak kurang dari 62.000 kepala keluarga harus meninggalkan rumah, mengungsi ke tempat yang mereka sendiri tidak tahu sampai kapan akan ditinggali.
Di tengah kenyataan sekelam itu, pertanyaan yang paling mengganggu justru bukan “mengapa bencana ini terjadi?”, tetapi: “Apakah kita masih merasa terkejut?”
Kita hidup di negeri yang secara geografis memang dikelilingi potensi bencana. Gunung berapi, patahan tektonik, curah hujan tinggi—semuanya adalah bagian dari takdir geologis yang tidak bisa kita negosiasikan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah manajemen risikonya, mitigasinya, dan kesiapsiagaannya.
Yang membuat opini ini pahit adalah kesadaran bahwa sebagian besar kerusakan bukan semata-mata soal alam yang sedang marah, tetapi soal kita—manusia—yang terus lalai.
Ketika hutan ditebang tanpa kendali, bukankah longsor sedang disiapkan? Ketika sungai disempitkan bangunan, bukankah banjir lambat-laun sedang ditulis? Ketika tata ruang diperlakukan sebagai formalitas, bukan panduan hidup, bukankah bencana tinggal menunggu jam?
Kita sering menyebut bencana sebagai “musibah”, seolah sepenuhnya terjadi tanpa campur tangan manusia. Padahal, banyak dari kejadian ini adalah hasil dari kombinasi sempurna antara ketidakpedulian struktural dan kelalaian kolektif—hari demi hari, tahun demi tahun.
Bumi boleh lelah, tapi kitalah yang membuat lelah itu menjadi amarah.
Namun, tulisan ini bukan sekadar ajakan untuk menunjuk siapa yang salah. Opini ini bukan tentang mencari kambing hitam. Ini adalah ajakan untuk menengok cermin.
Bencana yang terjadi minggu ini di Sumatra adalah sebuah undangan—undangan bagi kita untuk kembali menggunakan kepekaan kita sebagai manusia. Bukan hanya masyarakat umum yang harus tergerak, tetapi juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemilik modal, perencana kota, bahkan pembuat kebijakan yang menandatangani izin-izin krusial.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan terpenting adalah: Apa yang akan kita lakukan setelah ini?
Apakah kita akan kembali melupakan ketika berita baru berhenti muncul? Apakah kita akan kembali menunggu bencana berikutnya untuk kembali ribut? Apakah kita akan kembali membiarkan curah hujan menjadi pihak yang lebih disiplin daripada mitigasi kita?
Negara yang hidup di wilayah rawan bencana bukan negara yang harus pasrah. Negara seperti itu harusnya menjadi negara paling siap. Negara yang paling cekatan, paling tangguh, paling presisi.
Kita sudah punya struktur, lembaga, dan pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya respon cepat, tetapi perubahan cara berpikir. Kita perlu mengubah paradigma dari “menunggu bencana lalu bereaksi” menjadi “menjaga lingkungan dan ruang hidup sebelum bencana memaksa kita bereaksi.”
Dalam setiap bencana, selalu ada dua kerusakan: kerusakan yang bisa dilihat, dan kerusakan yang tak terlihat.
Yang bisa dilihat: rumah hancur, jembatan ambruk, jalan terputus, tanah runtuh, air bah. Yang tak terlihat: trauma yang menetap, kehilangan yang tak terucapkan, dan nurani yang perlahan kehilangan sensitivitas.
Dan menurut saya, kerusakan terakhir itulah yang paling membahayakan masa depan.
Jika ratusan korban jiwa masih belum membuat kita berhenti sejenak untuk merasakan kepedihan ini, berarti ada yang patah dalam diri kita sebagai bangsa. Jika puluhan ribu pengungsi masih belum membuat kita bertanya, “apa yang salah dari cara kita menjaga tanah ini?”, berarti kita telah membiarkan bencana menjelma sebagai rutinitas.
Kita tidak sedang dikalahkan oleh alam. Kita sedang dikalahkan oleh kelalaian kita sendiri.
Sumatra telah memberi kita peringatan. Pertanyaannya: apakah kita mau benar-benar belajar, atau kita hanya sedang menunggu berita duka berikutnya?
Sebab jika bencana sebesar ini pun tak lagi mengejutkan kita, itu berarti kita sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rumah, jembatan, atau harta benda: kita kehilangan nurani, dan kita tentu tak berharap angka-angka itu bertambah. (***)
Penulis: Djoni Satria/Wartawan Senior