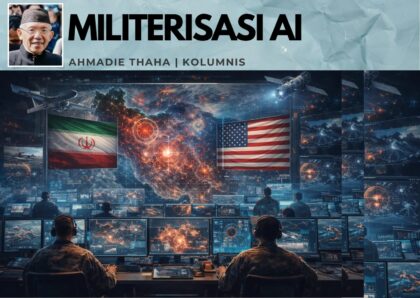RUZKA INDONESIA — Pagi di Depok selalu dibuka dengan deru. Deru mesin, deru langkah, deru orang-orang yang hidup di antara kenyataan bahwa sebagian besar waktu mereka bukan milik mereka sendiri.
Matahari baru memanjat di balik menara masjid, ketika gelombang manusia mulai bergerak menuju stasiun, jalan raya, terminal, dan halte—jalur-jalur panjang menuju Jakarta, pusat kerja yang tak pernah cukup dekat.
Di kota ini, seseorang bisa menghabiskan hidup tanpa benar-benar tinggal di dalamnya; tubuh menetap di Depok, tetapi pikirannya dipagari jam masuk kantor di Sudirman, Kuningan, atau Thamrin.
Dan dalam arus keseharian yang terus menyeret, data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti jendela kecil yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya warga Depok bertahan.
Pada tahun 2024, BPS Kota Depok merilis Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga. Angkanya tampak sederhana, tapi di balik angka itu ada ritme hidup, denyut kota, dan cerita sunyi yang diam-diam meletakkan fondasinya.
Dan di sanalah kejutan itu muncul: kelompok konsumsi terbesar bukanlah makanan, bukan pula biaya sekolah anak, bukan kesehatan, bukan pakaian atau perabot rumah. Yang terbesar justru adalah Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya—dengan porsi 33,34 persen.
Angka itu seperti mengetuk pintu kesadaran: warga kota ini tidak hidup dari apa yang mereka makan, melainkan dari bagaimana mereka bergerak.

Kota yang Digerakkan oleh Perjalanan
Setiap pagi, Sari—seorang guru honorer di Cilodong—berangkat pukul lima. Ada dua anak yang harus dibangunkannya, dua kotak bekal yang harus disiapkan, lalu dua cium di kening kecil yang masih terkantuk. Setelah itu dia berjalan cepat ke angkot. Ongkosnya naik, bensin naik, tapi gajinya tidak ikut naik. Sari tidak membaca laporan BPS, tapi ia menghidupinya setiap hari.
Ketika BPS menempatkan konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya sebagai komponen pengeluaran terbesar warga Depok, kita melihat Sari di dalam statistik itu. Kita melihat ojek-ojek yang sudah hilang suaranya sejak subuh. Kita melihat antrean panjang KRL, tiket pesawat murah yang jarang benar-benar murah, pulsa internet yang jadi kebutuhan primer seperti beras dan minyak goreng.
Transportasi menjadi nomor satu bukan karena warga Depok ingin bepergian jauh—tetapi karena mereka terpaksa melakukannya.
Depok adalah kota penyangga, kota yang hidup dari arus pekerja yang keluar masuk setiap hari. Ketergantungan pada Jakarta bukan hanya relasi ekonomi, tapi juga relasi waktu, relasi tenaga, relasi jarak emosional antara rumah dan kehidupan yang ingin diraih.
Bagi jutaan commuter, transportasi bukan sekadar perjalanan. Ia adalah harga dari kesempatan.
Isi Perut Nomor Dua
Dalam laporan yang sama, konsumsi makanan, minuman, dan rokok selain restoran berada di posisi kedua—32,56 persen. Angka yang hanya berbeda tipis dari posisi pertama, namun cukup untuk membuat warga Depok tertawa pahit: bahkan isi perut pun harus rela berada di urutan kedua.

Dari mana datangnya ironi ini?
Di warung kecil dekat Terminal Depok, Rizal—seorang sopir angkot—mengaduk kopi sachet sambil menghitung receh. “Yang penting bensin cukup,” katanya. “Lapar bisa nunggu.”
Barangkali di situlah benang merahnya: transportasi menjadi kebutuhan utama bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk makan. Untuk mendapatkan upah, seseorang harus membayar ongkos pergi ke tempat yang menawarkan pekerjaan. Circular logic yang membuat sebagian warga seperti berjalan di treadmill: bergerak cepat, tapi tetap di tempat.
Angka 32,56 persen bukan sekadar porsi belanja, tapi juga cermin dari bagaimana makanan di Depok tidak bisa hadir tanpa perjalanan panjang yang mendahuluinya.
Rumah Bukan Tempat Paling Banyak Dihuni
Komponen konsumsi lain seperti perumahan dan perlengkapan rumah tangga (8,68 persen) atau kesehatan dan pendidikan (7,01 persen) tampak kecil jika dibandingkan dua kelompok belanja terbesar tadi.
Sungguh menarik bila kita bayangkan: warga Depok menghabiskan lebih banyak uang untuk mobilitas daripada untuk rumah, lebih banyak untuk pulsa internet daripada untuk pendidikan anak.
Depok adalah kota yang terus tumbuh terlalu cepat. Jalan-jalannya dipenuhi kembang-kempis urbanisasi, perumahan baru muncul seperti jamur, apartemen dibangun di setiap sudut, namun ruang hidup warganya tetap terasa sempit. Mereka tinggal di Depok, tapi sebagian besar hidupnya dihabiskan di luar kota.
Pulsa internet—yang menjadi bagian dari kelompok komunikasi—bahkan telah menjadi tiket untuk tetap terhubung dengan dunia. Tanpa internet, seseorang tak bisa bekerja, belajar, atau sekadar berbicara dengan keluarga.
Jika rumah adalah tempat kembali, maka komunikasi adalah jembatan agar seseorang tetap merasa punya rumah.
Rekreasi dan Budaya: Nafas Pendek di Tengah Sesak
Angka kelompok konsumsi ini tak hanya mencakup transportasi dan komunikasi, tapi juga rekreasi dan budaya. Dan bagian inilah yang sering tak disadari.
Pada akhir pekan, warga Depok memadati taman, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat makan, hingga kebun raya. Mereka mencari ruang bernapas setelah hari-hari penuh macet dan tekanan. Rekreasi menjadi kompensasi atas lelah yang menumpuk. Budaya menjadi pintu kecil untuk mengingat bahwa mereka punya identitas, bukan sekadar nomor dalam gerbong KRL.
Mungkin inilah alasan mengapa Depok masih hidup: manusia selalu mencari alasan untuk bertahan.
Angka-Angka yang Mengandung Wajah
Data BPS 2024 juga menunjukkan kelompok lain:
• Pakaian dan alas kaki: 2,20 persen.
Warga Depok tidak membeli baju setiap bulan; mereka membeli waktu untuk mencapai tempat kerja.
• Hotel dan restoran: 12,58 persen.
Angka ini menandakan gaya hidup urban—makan di luar, memesan makanan daring, atau sekadar ngopi untuk tetap waras.
• Lainnya: 3,62 persen.
Sisanya adalah kebutuhan-kebutuhan kecil yang tidak diberi nama, tetapi justru sering menjadi alasan seseorang tersenyum hari itu.
Statistik selalu dingin, tapi wajah-wajah yang menyusunnya hangat dan hidup.
Depok dan Masa Depan yang Sedang Dirundingkan
Angka-angka konsumsi menunjukkan arah kota tanpa harus membaca rencana pembangunan jangka panjang. Ketika pengeluaran terbesar adalah transportasi, maka Depok sedang dalam proses mencari bentuk. Kota ini ingin menjadi mandiri, namun kenyataan membuatnya tetap menjadi kota penyangga.
Transportasi adalah tulang punggung sekaligus beban. Komunikasi adalah alat bertahan sekaligus pengingat betapa hidup semakin digital. Rekreasi dan budaya adalah ruang penyembuhan bagi warga yang terlalu lelah mengejar waktu.
Satu hari nanti, mungkin Depok ingin menjadi kota yang tidak lagi memaksa warganya untuk hidup dalam ritme dua kota. Kota yang memungkinkan seseorang bekerja di tempat ia tinggal. Kota yang memprioritaskan isi perut di atas ongkos perjalanan.
Tetapi hingga hari itu tiba, Depok tetap menjadi kota yang hidup dari perjalanan panjang warganya.
Dan di antara deru yang tak pernah padam, data BPS tahun 2024 itu berdiri sebagai cermin paling jujur: kita menghabiskan lebih banyak uang untuk pergi daripada untuk hidup. (***)
Penulis: Djoni Satria/Wartawan Senior