RUZKA INDONESIA — Banyak kawan bertanya pada saya, apakah betul NU sedang jadi target untuk diobok-obok dan dihancurkan demi kepentingan politik tertentu, sebagaimana dulu pernah terjadi pada NU di masa KH Abdurrahman Wahid? Apakah betul NU dikondisikan untuk menjadi objek politik, terutama untuk persiapan Pemilu 2029?
Dari situ kemudian muncul bayangan di benak saya —sekadar bayangan liar, tapi terlalu logis untuk diabaikan— bagaimana jika: sebuah organisasi keagamaan yang selama ini hidup dari kotak amal, wakaf tanah sawah, dan keikhlasan santri, tiba-tiba menggenggam potensi duit Rp 160 triliun? Anggap saja —sekadar andaian— NU punya duit segitu lima tahun ke depan. Aminkan. Amin.
Betulan, angka Rp 160 triliun itu bukan hasil mimpi setelah makan nasi kebuli tengah malam, melainkan hitung-hitungan sederhana mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Ia menyebut bahwa lahan tambang seluas 25 ribu hektar untuk NU itu mengandung potensi satu miliar ton batubara kelas A. Kalikan angka itu dengan fee sekitar sepuluh dolar per ton yang akan diterima dari pengelola.
Dengan model kerjasama yang jamak dilakukan seperti itu, menurut Pak Dahlan, NU tak perlu repot mengeruk, tidak pusing memikirkan harga batubara dunia, tidak perlu mengurus debu, limbah, atau kalau mau boleh juga bantu-bantu jika ada protes LSM. Cukup duduk manis, tanda tangan kontrak, lalu uang akan mengalir deras tiada henti seperti sungai di musim hujan.
Maka sejak detik itu, NU tak lagi sekadar kekuatan moral yang fasih memberi nasihat dari mimbar, tapi menjelma jadi satu kekuatan strategis yang bisa menggerakkan papan catur politik nasional. Dengan punya modal besar, mesin politik bisa digerakkan dengan mudah, apalagi NU sudah berpengalaman jadi partai politik dan punya jaringan sumber daya hingga pelosok negeri.
Di titik ini, jika nantinya sudah punya dana triliunan, sejarah NU seperti sedang dibelokkan secara halus namun tegas. Selama ini, selama puluhan tahun, NU umumnya dikenal hanya sebatas penentu arah moral: memberi legitimasi, menenangkan gejolak, atau menarik rem darurat ketika negara nyaris tergelincir ke lumpur.
Tapi kekuatan moral punya satu kelemahan klasik: ia miskin logistik. Begitu logistik datang —dan bukan logistik receh, tapi triliunan— peta berubah. Kiai yang biasanya bicara maslahat umat, tiba-tiba harus memahami istilah AMDAL, WIUPK, cashflow, dan operator tambang. Kitab kuning bersisian dengan proposal bisnis. Doa qunut berdampingan dengan kalkulator.
Di sinilah uang mulai cerewet. Angka Rp160 triliun versi hitungan Pak Dahlan itu tidak datang dengan wajah polos. Ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang licik: dipakai untuk apa, dikelola oleh siapa, dan —yang paling sensitif— untuk kepentingan siapa. Tak cukup transparansi, warga juga merasa berhak memperoleh bagian.
Dalam iklim politik menuju 2029, pertanyaan itu berubah menjadi desas-desus. NU dengan tambang berarti NU dengan mesin logistik mandiri. Mesin seperti ini terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan liar. Ia harus dipastikan seirama dengan kepentingan kekuasaan yang sedang menata barisan menuju periode berikutnya.
Maka jangan heran jika kemudian muncul macam-macam dugaan, seperti bahwa sejak isu tambang menyeruak, dan dibumbui isu uang bernilai miliaran, NU tak lagi tenang. Konflik internal yang biasanya diselesaikan dengan musyawarah dan kopi pahit diselilingi guyonan khas santri, kini beraroma strategi tingkat tinggi.
Tambang menjadi magnet yang menarik politisi, pengusaha, dan birokrat ke dalam orbit NU. Bukan untuk mengaji, tapi untuk memastikan satu hal: ke mana arah kekuatan baru ini akan bergerak tiga-empat tahun ke depan. Apakah ia akan tetap menjadi penyangga moral negara, atau berubah menjadi pemain aktif dalam perebutan kekuasaan?
Dalam konteks ini, posisi ketua umum bukan lagi sekadar jabatan organisasi, melainkan simpul strategis. Ia bukan hanya memimpin jam’iyyah, tapi memegang kunci ke aset bernilai ratusan triliun. Ketika kunci itu berada di tangan sosok yang terlalu independen, terlalu vokal, dan terlalu sulit ditebak, kegelisahan pun lahir.
Politik, seperti kita tahu, paling alergi pada ketidakpastian, pada pribadi yang sulit ditebak. Oposisi bisa dilawan, kritik bisa diredam, tapi independensi yang tak bisa diprediksi adalah mimpi buruk bagi para perencana kekuasaan. Teori politik inilah yang menjadi dasar analisis yang kadang berlebihan.
Pertanyaan-pertanyaan seperti: Mengapa semua penggantian ini terasa dilakukan tergesa? Mengapa tidak menunggu muktamar saja, forum tertinggi yang sah dan bermartabat itu? Jawabannya sederhana dan ironis: justru karena muktamar sah, ia berbahaya. Di sana legitimasi bekerja, suara akar rumput bicara, dan drama kekuasaan bisa berbalik arah.
Dalam logika politik, lebih aman merapikan papan sebelum permainan dimulai, daripada menunggu bidak bergerak sendiri. Begitulah, banyak wacana dan analisa bermunculan menanggapi kisruh di tubuh NU. Pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat diselenggarakan membawa segala rumor baik yang recehan maupun masuk akal.
Menurut sebagian mereka, tambang ini, yang semula disebut-sebut sebagai berkah ekonomi umat, pelan-pelan menampakkan wajah lain. Ia bukan sekadar lubang di tanah berisi batubara, tapi lubang ujian bagi NU. Ujian apakah organisasi ini mampu mengelola kekayaan tanpa kehilangan arah, mampu memegang kekuasaan tanpa mabuk kuasa, dan mampu tetap menjadi penuntun moral di tengah godaan menjadi pemain strategis.
Ironinya, NU mungkin tak pernah meminta tambang itu. Tapi ketika tambang sudah di tangan, menolaknya tak semudah menolak amplop. Sejarah jarang memberi pilihan yang bersih. Ia lebih suka menyodorkan dilema: ambil berkahnya, tapi tanggung risikonya. Dan di sinilah NU berdiri hari ini, di persimpangan antara khittah dan kekuasaan, antara doa dan dolar, antara menjadi cahaya penuntun atau mercusuar politik.
Walhasil, mungkin kita perlu membalik cara pandang. Bukan bertanya apakah NU pantas punya tambang, tapi apakah tambang pantas masuk ke NU. Sebab kekuatan moral, ketika bersentuhan dengan kekuatan ekonomi dan politik, selalu diuji bukan oleh musuh, melainkan oleh godaan. Dan sering kali, yang paling berbahaya bukan serangan dari luar, tapi bisikan halus dari dalam: “Sayang kalau dilepas.” (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 30/12/2025


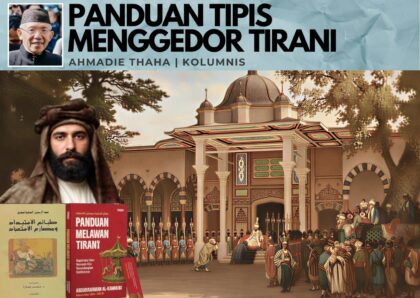



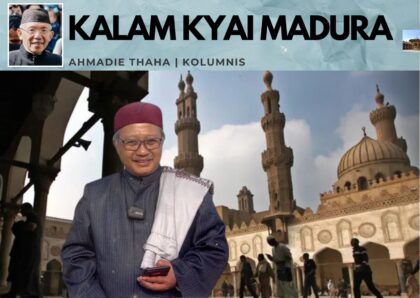

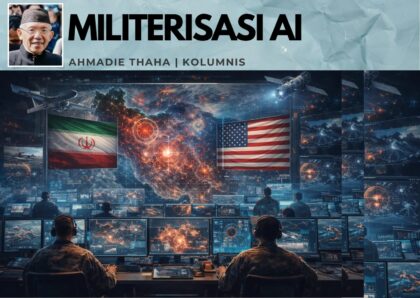












Komentar