RUZKA INDONESIA — Undangan FGD (diskusi kelompok terpumpun) itu datang dengan gaya khas birokrasi: ramah, sopan, hangat, dan mendadak.
Saya kira cukup duduk manis, mendengar, lalu pulang dengan sertifikat. Ternyata tidak. Saya justru didaulat duduk di deretan pembicara utama, berdampingan dengan dua nama lain.
Acara diselenggarakan Dr. H. Adib, M.Ag., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
Temanya agung dan bercahaya: penyiapan dan pelayanan umat masa depan menuju Indonesia Emas. Emas, tentu saja, logam mulia yang selalu mengkilap di pidato, meski kadang di lapangan masih berupa loyang.
Kang Adib, panggilannya, menekankan moderasi beragama sebagai komponen penting menuju masa depan itu. Saya sepakat, tetapi langsung gelisah pada satu kata: moderat. Kata ini sudah terlalu sering diperlakukan seperti posisi duduk di bus ekonomi — di tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, asal tidak ribut.
Moderat lalu dipahami sebagai sikap “aman”, kompromistis, toleran, tidak ekstrem, cenderung abu-abu, bahkan kadang dicurigai tak punya pendirian. Seolah yang keras itu pasti ekstrem, yang lunak pasti plin-plan, dan yang moderat adalah mereka yang berdiri di antara dua kutub sambil mengipas-ngipas suasana.
Padahal, dalam tradisi Islam klasik, moderasi justru bukan soal berdiri di tengah secara geometris, melainkan soal keluasan dada. Ia bukan hasil kalkulasi jarak dari dua ekstrem, melainkan hasil latihan intelektual dan spiritual untuk hidup bersama perbedaan, bahkan perbedaan yang tajam dan menyebalkan.
Dalam hampir setiap kitab tafsir dan fikih, para ulama tidak sedang mencari satu pendapat paling aman, tetapi justru memaparkan keragaman pandangan. Kitab tafsir karya Muhammad ibnu Jarir al-Tabari, misalnya, penuh dengan kutipan pendapat ulama lain, termasuk kabar-kabar Israiliyyat yang hari ini sering membuat kening berkerut.
Itu bukan karena beliau ceroboh, melainkan karena ia sadar: memahami wahyu membutuhkan peta pendapat para ulama yang memang berbeda-beda. Peta itu lalu disaring dan dirapikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang lebih ramping, lebih selektif, dan lebih “ramah santri”.
Di bidang fikih, kita mengenal Ar-Risalah karya Muhammad ibnu Idris al-Shafi’i, dan tentu saja Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Khazanah Islam kaya dengan kitab-kitab serupa yang menampilkan perbedaan mazhab secara terbuka. Kitab-kitab ini bukan buku panduan satu jawaban, melainkan atlas perbedaan.
Ia mengajarkan bahwa tidak sepakat itu normal, dan yang tidak normal justru adalah mengira hanya diri sendirilah pemegang kebenaran tunggal. Kitab-kitab semacam inilah yang diajarkan di pesantren, mulai dari pesantren tradisional hingga yang mengalur jalur muadalah mu’allimin.
Maka jangan heran bila alumni lembaga pendidikan seperti Pesantren Gontor atau Al-Amien Prenduan tampak relatif tenang menghadapi perbedaan, tidak mudah gusar, dan luwes bergerak di ruang demokrasi. Mereka sejak dini dilatih hidup bersama banyak jawaban, tanpa harus kehilangan keyakinan.
Pada titik inilah saya teringat kisah dari belahan dunia lain, dari seorang profesor hukum dan agama bernama John Inazu. Ia mengajar di Washington University dan pada 2024 menulis buku berjudul Learning to Disagree (Belajar Berbeda).
Buku ini lahir dari pengalaman nyata di kelas, bukan dari menara gading teori resolusi konflik. Salah satu kisah paling menarik adalah tentang mahasiswinya, Jennifer Chang — cerdas, percaya diri, dan keras kepala sampai-sampai Inazu sempat memberi cap “unteachable”, label akademik yang lebih kejam dari nilai E.
Jennifer datang dengan kepastian moral yang nyaris absolut. Ia ingin mengkritik seorang tokoh klasik sebagai perusak kehidupan sipil, terutama karena pandangannya tentang perempuan. Ketika Inazu menyarankan agar ia memperkaya konteks sejarah dan menanggapi argumen terbaik dari tokoh yang ia kritik, Jennifer menolak.
Dua bulan kemudian, draf tulisannya datang. Isinya malah lebih keras, lebih marah, dan lebih sempit. Inazu lalu melakukan sesuatu yang hari ini terasa hampir radikal: ia memberi umpan balik jujur dan tegas, tanpa memanjakan, tanpa membungkus kritik dengan gula empati berlebihan.
Ia meminta Jennifer belajar satu hal sederhana tapi berat: bagaimana cara tidak setuju dengan baik. Belajar untuk berbeda. Belajar untuk esa tunggal eka, tetap bersatu meski beragam pikiran. Indonesia banget.
Dua bulan berikutnya, sebuah makalah datang, diselipkan di bawah pintu kantornya. Isinya membuat Inazu terdiam. Jennifer tetap tidak setuju, bahkan tetap kritis, tetapi kini tulisannya bernuansa, tajam, dan adil. Ia tidak lagi membuat karikatur lawannya, tidak menghakimi pendapat yang berbeda hanya dari sudut pandangnya sendiri.
Berkat saran Inazu, rupanya ia belajar membedakan antara keyakinan normatif dan fakta, antara kecaman dan argumentasi. Yang berubah bukan pendapatnya, melainkan caranya memperlakukan perbedaan. Inazu pun tersadar bahwa ia sendiri sempat terjebak dalam dosa intelektual yang sama: menghakimi terlalu cepat.
Kisah ini terasa akrab dengan tradisi pesantren dan kitab-kitab klasik tadi. Moderasi bukan berarti melembekkan keyakinan, tetapi mengeraskan disiplin berpikir dan melembutkan cara bersikap. Ia bukan soal mencari titik tengah, melainkan soal kesediaan menampung banyak suara tanpa harus kehilangan arah.
Dalam konteks Indonesia Emas, mungkin justru inilah emas yang paling sulit ditambang: kemampuan untuk berbeda tanpa saling membatalkan, untuk keras pada argumen namun lembut pada manusia. Inilah emas yang mesti dihadiahkan bagi generasi Z yang diharapkan mencemerlangkan Indonesia pada 2045.
Moderasi selama ini kerap difokuskan pada bidang keagamaan, lalu dipadankan dengan istilah wasathiyah. Konsep ini banyak diwacanakan dan dipraktikkan oleh ormas-ormas Islam arus utama seperti Persatuan Ummat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.
Pada ranah negara, penguatan moderasi beragama secara institusional ditangani oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Fokusnya pada perumusan kebijakan strategis, penguatan kerukunan dan toleransi, serta perumusan Indeks Moderasi Beragama.
Selain itu, terdapat Sekretariat Bersama Moderasi Beragama yang mengoordinasikan berbagai program lintas unit, serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (meliputi Bimas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya) yang aktif membina masyarakat akar rumput, termasuk inisiatif “Desa Moderasi Beragama”.
Penguatan ini juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme guna mencegah radikalisme. Secara konseptual, seluruh upaya tersebut bertumpu pada empat pilar utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal.
Akhirnya, mungkin moderasi seharusnya bukan proyek penjinakan umat, melainkan proyek pendewasaan. Bukan agar semua sepakat, tetapi agar yang tidak sepakat tetap bisa duduk satu meja tanpa saling melempar kursi. Boleh memakai istilah moderasi, atau bahkan wasathiyah. Silakan saja.
Jika itu tercapai, barangkali Indonesia Emas bukan lagi sekadar slogan berkilau di baliho, melainkan hasil dari latihan panjang yang ditularkan dan dibiasakan hingga menjadi budaya, pada generasi harapan bangsa: belajar tidak setuju, tanpa kehilangan hormat — dan tanpa kehilangan akal. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 13/2/2026

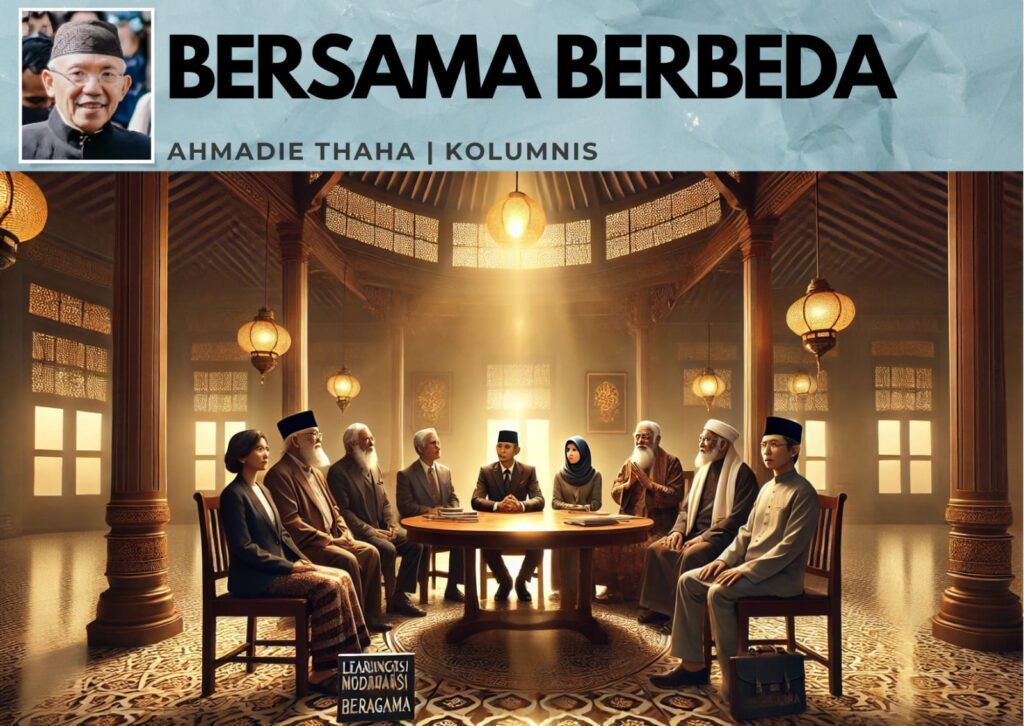
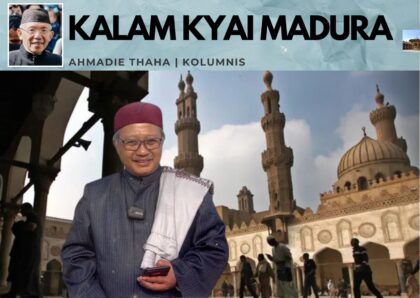

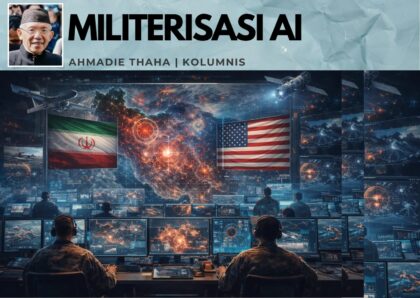
















Komentar